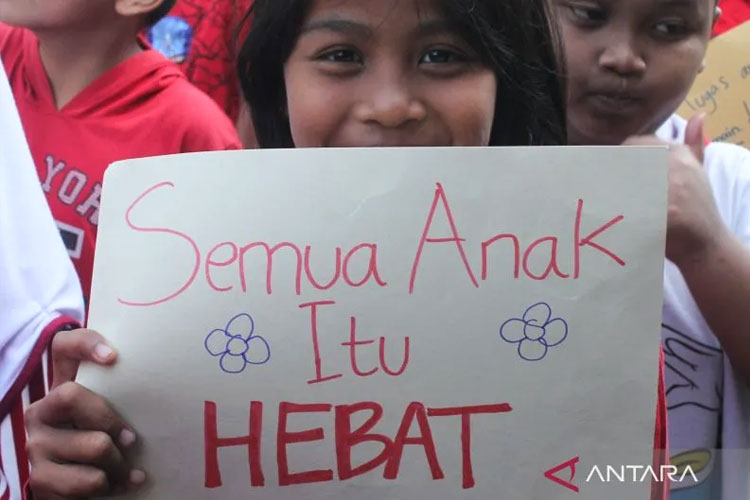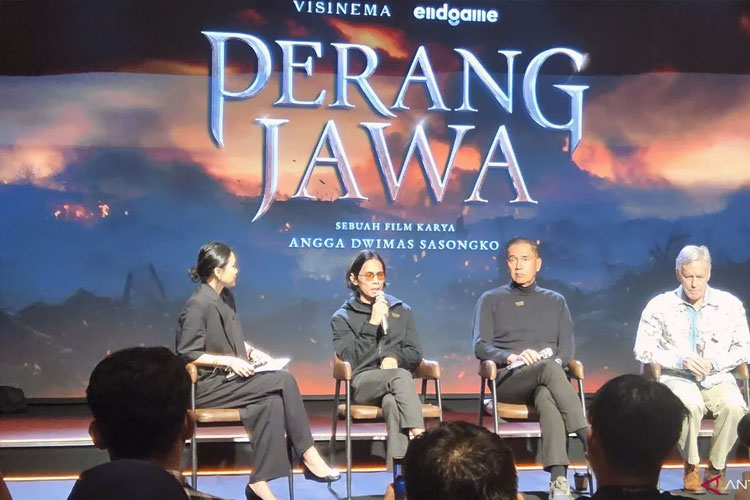TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dalam sistem demokrasi yang ideal, partai politik seharusnya menjadi wahana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang berbasis pada ideologi. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, ideologi partai sering kali bersifat ambigu, cair, dan tidak konsisten.
Sengkarut ideologi partai politik di Indonesia mencerminkan kondisi di mana perbedaan ideologis antar partai sulit untuk diidentifikasi secara tegas. Partai-partai kerap menyatakan komitmen terhadap prinsip-prinsip tertentu, tetapi dalam praktik politiknya justru menunjukkan sikap yang kontradiktif.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah politik di Indonesia, sistem elektoral yang terbuka, serta budaya politik klientelistik yang masih mengakar kuat.
Polarisasi Ideologis dan Dinamika Politik PSI
Studi Fossati et al. (2020) menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia tidak terpolarisasi secara signifikan dalam isu ekonomi. Hampir seluruh partai cenderung mendukung kebijakan populis dengan intervensi negara dalam ekonomi serta program sosial untuk kelas menengah dan bawah.
Bahkan partai-partai yang secara historis lahir dari tradisi nasionalis atau Islamis pun kerap menyampaikan program ekonomi serupa. Ini menyebabkan preferensi pemilih tidak terpetakan secara programatik dalam dimensi ekonomi.
Polarisasi ideologis yang nyata justru terlihat dalam isu hubungan antara negara dan agama, khususnya peran Islam dalam politik. Melalui Political Islam Index (PII), ditemukan bahwa posisi partai terhadap isu keagamaan cukup beragam dan mencerminkan spektrum antara kelompok Islamis hingga pluralis.
Partai seperti PKB, PPP dan PKS menunjukkan kecenderungan kuat mendukung peran Islam dalam politik, sementara PDI-P, Golkar, dan NasDem cenderung pluralis dan sekuler. Akan tetapi, sekalipun terdapat perbedaan ideologis ini, koalisi lintas partai sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesesuaian ideologis, melainkan didasarkan pada kepentingan kekuasaan dan distribusi sumber daya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam demokrasi klientelistik seperti Indonesia, ideologi tidak berfungsi sebagai jangkar utama dalam pembentukan aliansi politik maupun dalam penyusunan kebijakan. Sebaliknya, logika transaksional dan daya tarik elektoral menjadi faktor dominan.
Salah satu fenomena politik yang menarik perhatian dalam dekade terakhir adalah kemunculan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Didirikan oleh anak-anak muda perkotaan dengan latar belakang aktivisme dan profesionalisme, PSI mengusung identitas sebagai partai yang progresif, pluralis, dan antikorupsi.
Secara eksplisit, PSI menolak perda-perda berbasis agama, mempromosikan kebebasan beragama, hak-hak minoritas, dan kesetaraan gender. Dalam banyak hal, PSI berusaha membedakan dirinya dari partai-partai lama yang dianggap konservatif dan korup.
Di ruang publik, PSI kerap tampil sebagai pelindung nilai-nilai kebhinekaan dan menjadi antitesis terhadap menguatnya politik identitas berbasis agama.
Namun lebih dari itu, PSI juga memperoleh sorotan karena dukungan terbuka yang diterimanya dari keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, menunjukkan kedekatan politik dengan PSI dalam berbagai momen.
Bahkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, secara resmi bergabung dan menjabat sebagai Ketua Umum PSI sejak 2023 dan terpilih kembali untuk masa periodesasi 2025-2030.
Di bawah kepemimpinan Kaesang, PSI melakukan rebranding besar, termasuk mengganti logo partai menjadi gambar gajah yang disebut sebagai simbol solidaritas, kekuatan kolektif, dan kesetiaan.
Langkah ini memberikan angin segar bagi PSI dalam memperluas jangkauan politiknya, tetapi sekaligus mengaburkan klaim PSI sebagai partai yang sepenuhnya anti-dinasti dan antiklientelisme.
Masuknya Kaesang ke dalam PSI memperkuat persepsi bahwa partai ini memanfaatkan jejaring kekuasaan untuk memperoleh legitimasi politik, sebuah tindakan yang kontras dengan semangat antikorupsi dan meritokrasi yang selama ini mereka kampanyekan.
Konsistensi Ideologi Partai di Negara Lain
Dalam membandingkan situasi di Indonesia, penting untuk melihat bagaimana partai politik di berbagai negara lain mempertahankan konsistensi ideologi mereka sebagai landasan utama dalam berpolitik. Beberapa negara menunjukkan bagaimana ideologi berperan sentral dalam program partai, aliansi politik, hingga perilaku pemilih.
Di Jerman, misalnya, partai-partai utama seperti Christian Democratic Union (CDU) dan Social Democratic Party (SPD) memiliki garis ideologis yang jelas. CDU berakar pada nilai-nilai konservatif dan Kristiani, sedangkan SPD mengusung ideologi sosial-demokrat yang pro-kesejahteraan dan berorientasi kelas pekerja.
Konsistensi ini tidak hanya terlihat dalam platform kebijakan, tetapi juga dalam tradisi politik internal dan sikap kader partai terhadap isu-isu sosial dan ekonomi.
Di Amerika Serikat, walaupun sistemnya dua partai besar, perbedaan ideologis antara Partai Demokrat dan Partai Republik sangat kentara. Partai Demokrat cenderung mengusung progresivisme dalam isu lingkungan, hak-hak sipil, dan ekonomi redistributif.
Sedangkan Partai Republik lebih konservatif dalam hal pajak, peran negara, serta isu sosial seperti aborsi dan kepemilikan senjata. Polarisasi ini bahkan semakin menguat dalam dua dekade terakhir, mencerminkan betapa kuatnya peran ideologi dalam struktur politik Amerika.
Sementara itu, di Inggris, Partai Buruh memiliki basis ideologis sosialis demokrat, dengan akar kuat dalam serikat pekerja, sedangkan Partai Konservatif mendorong pasar bebas, nilai-nilai keluarga, dan nasionalisme Inggris.
Di Prancis, partai-partai seperti La France Insoumise (kiri-radikal) dan Rassemblement National (kanan-populis) secara terang-terangan mengusung ideologi yang kontras dalam seluruh aspek kampanye dan legislasi.
Negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia juga menunjukkan bahwa stabilitas ideologi dalam partai berkontribusi pada kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan. Partai Sosial Demokrat di negara-negara tersebut telah lama memperjuangkan negara kesejahteraan berbasis pajak progresif, dan tetap konsisten meski mengalami pergantian kepemimpinan dan koalisi.
Dari studi perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem politik yang mendorong akuntabilitas programatik dan institusionalisasi partai yang kuat berkontribusi pada keberlangsungan ideologi sebagai pilar utama partai.
Sebaliknya, dalam sistem politik yang cenderung pragmatis dan klientelistik, seperti di Indonesia, ideologi partai sering kali berubah menjadi alat simbolik belaka.
Kehadiran PSI, dalam konteks ini, menambah dimensi baru dalam sengkarut ideologi partai politik Indonesia. Di satu sisi, PSI menawarkan diferensiasi ideologis yang lebih jelas dalam isu-isu sosial dan budaya, terutama dalam menghadapi arus konservatisme agama.
Di sisi lain, konsistensi ideologis PSI dipertanyakan karena absennya platform ekonomi yang sistematis serta praktik politik yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi internal partai.
Hal ini menegaskan bahwa bahkan partai baru yang mengklaim diri progresif pun tidak imun terhadap kompleksitas sistem politik klientelistik dan personalistik di Indonesia.
Lebih luas, ketidakkonsistenan ideologis ini merupakan cerminan dari sistem politik Indonesia secara keseluruhan, di mana insentif elektoral lebih mengutamakan pencitraan, akses terhadap sumber daya, dan afiliasi personal ketimbang keberpihakan ideologis yang kokoh.
Dalam iklim politik seperti ini, pemilih kerap kali dihadapkan pada pilihan-pilihan partai yang secara simbolik berbeda, tetapi secara substantif memiliki pola perilaku politik yang serupa.
Dengan demikian, sengkarut ideologi partai politik Indonesia merupakan konsekuensi dari interaksi antara struktur kelembagaan yang lemah, budaya politik yang pragmatis, serta insentif elektoral yang lebih mendorong pencitraan daripada pematangan ideologis.
Meskipun terdapat sumbu ideologis yang masih bertahan, khususnya dalam isu agama, mayoritas partai cenderung bersikap fleksibel dalam koalisi maupun kebijakan.
Dalam situasi seperti ini, pemilih mengalami kesulitan untuk membedakan partai berdasarkan program ideologis yang konsisten. Untuk memperkuat kualitas demokrasi representatif di Indonesia, diperlukan pelembagaan partai yang lebih kuat, kaderisasi berbasis ideologi, dan pembenahan sistem elektoral agar mendorong akuntabilitas programatik, bukan sekadar populisme dan patronase.
***
*) Oleh : Asyraf Al Faruqi Tuhulele, Magister Departeman Ilmu Politik dan Pemerintah Universitas Gadjah Mada (DPP UGM).
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |