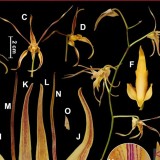TIMES JAKARTA, JAKARTA – Isu pangan tidak pernah menjadi persoalan yang selesai. Ia melekat dalam keseharian manusia, menjadi sumber energi, penentu produktivitas, bahkan cermin peradaban. Di tengah arus globalisasi, muncul pertanyaan mendasar: apakah makanan yang kita konsumsi hari ini masih mencerminkan jati diri bangsa serta memenuhi unsur halal dan thayib (baik bagi kesehatan tubuh)?
Pertanyaan ini patut direnungkan menjelang Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2025. Refleksi ini mengemuka pula dalam kegiatan Majelis Nyala Purnama yang digelar Direktorat Kebudayaan Universitas Indonesia bersama Komunitas Makara dan Urban Spiritual Indonesia, bertema “Makan Sehat, Jiwa Kuat, Bangsa Hebat”. Dari forum itu, saya menangkap satu hal penting: pangan bukan sekadar konsumsi, tetapi juga kebudayaan.
Dewasa ini, tradisi pangan masyarakat Indonesia menghadapi ambivalensi. Di satu sisi, kita berupaya memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat. Di sisi lain, produk lokal tergeser oleh makanan asing dan cepat saji. Bandingkan meja makan keluarga Indonesia tahun 1990-an dengan hari ini.
Dulu, ubi, singkong, sayur hijau, dan ikan segar menjadi menu harian. Kini, roti, burger, dan makanan kaleng lebih sering terhidang. Pergeseran pola konsumsi ini tak sekadar perubahan selera, tapi juga pergeseran nilai budaya.
Ki Hajar Dewantara pernah berkata, “Budaya adalah hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman.” Maka mempertahankan pangan lokal sejatinya adalah upaya mempertahankan budaya. Makanan adalah hasil perjuangan manusia atas alamnya dari sawah, laut, dan ladang yang diwariskan lintas generasi.
Selama ini, diskursus pangan kerap berhenti pada istilah ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Namun, cita-cita bangsa ini seharusnya melangkah lebih jauh menuju kedaulatan pangan: kemampuan masyarakat menentukan sendiri jenis, sumber, dan cara mereka memproduksi makanan.
Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (6 Agustus 2025) menegaskan, kemandirian pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan bangsa. Jenis pangan yang dikonsumsi sebuah bangsa adalah penanda identitas dan martabatnya. Artinya, kedaulatan pangan tak hanya soal ekonomi, tetapi juga eksistensi budaya.
Indonesia Kaya, Tapi Rawan Kehilangan Identitas
Indonesia sesungguhnya tak pernah miskin identitas, termasuk dalam soal pangan. Setiap daerah memiliki keunikan hasil bumi mulai dari sagu di wilayah timur hingga beras di bagian barat.
Dari perairan pun lahir kekayaan protein seperti ikan wader, bandeng, gurami, hingga hasil laut lainnya. Semua itu menggambarkan keberlimpahan yang jika dikelola dengan bijak, cukup memberi makan bangsa sendiri.
Tantangan kedaulatan pangan kian kompleks. Perubahan iklim yang ekstrem, penyusutan lahan pertanian, berkurangnya petani muda produktif, serta ketergantungan pada impor.
Data Kementerian Kehutanan (2024) mencatat, luas hutan Indonesia tinggal 95,5 juta hektare atau 51,1% dari total daratan. Deforestasi mencapai 175,4 ribu hektare per tahun dan sebagian besar terjadi karena ambisi ekonomi yang mengorbankan tanah subur penghasil pangan.
Di sisi lain, jumlah petani produktif terus menurun. Profesi petani dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi, padahal ketahanan pangan justru berdiri di atas kerja keras mereka. Ironisnya, saat pangan lokal terabaikan, kita justru bangga mengonsumsi produk impor yang belum tentu lebih bergizi.
Gaya hidup masyarakat pun berubah drastis. Konsep “empat sehat lima sempurna” yang dulu membentuk kebiasaan makan sehat kini tergantikan oleh tren makanan cepat saji.
Padahal, pola konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak jenuh terbukti meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Perubahan budaya makan ini menunjukkan bagaimana globalisasi menggeser selera sekaligus melemahkan kesadaran pangan lokal.
Pangan bukan sekadar persoalan ekonomi atau teknologi pengolahan, melainkan simbol kemandirian dan kebanggaan nasional. Setiap kali kita memilih produk lokal beras dari sawah sendiri, ikan dari nelayan kita, sayuran dari petani desa kita sejatinya sedang menghidupkan budaya dan martabat bangsa.
Kedaulatan pangan adalah bentuk cinta tanah air yang paling nyata. Ia menuntut kesadaran kolektif, bahwa setiap sendok nasi bukan sekadar sumber energi, tetapi juga identitas kebangsaan. Semakin bangga suatu bangsa pada pangannya sendiri, semakin kuat jati diri budayanya berdiri di tengah arus global.
Di momentum Hari Pangan Sedunia ini, refleksi kita seharusnya tidak berhenti pada ajakan makan sehat, tetapi juga makan dengan kesadaran budaya. Karena pada akhirnya, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mengenali dan menghargai pangan hasil tangannya sendiri.
***
*) Oleh : Abdurrahman Ad Dakhil, Mahasiswa S2 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |