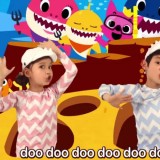TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pegunungan Meratus yang membentang di Kalimantan Selatan bukan hanya bentang alam yang indah, tetapi juga salah satu pusat keanekaragamasn hayati terpenting di Indonesia.
Dari perspektif geografi fisik, kawasan ini berperan sebagai water catchment area yang menyuplai air bersih bagi ribuan penduduk, menjadi penyangga iklim mikro, serta habitat bagi berbagai flora dan fauna endemik.
Namun, nilai Meratus tidak berhenti pada dimensi ekologis. Bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitarnya, hutan dan pegunungan ini adalah ruang hidup (living space) yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Meratus adalah lanskap budaya (cultural landscape), perpaduan antara alam dan manusia yang dibentuk melalui interaksi berabad-abad. Sistem ladang berpindah, penetapan kawasan hutan larangan, dan zonasi adat untuk melindungi sumber air merupakan contoh konkret bagaimana komunitas adat menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam.
Kontroversi Status Taman Nasional
Rencana pemerintah mengubah status Pegunungan Meratus menjadi taman nasional di atas kertas tampak ideal. Taman nasional identik dengan perlindungan ketat, pengawasan negara, dan promosi konservasi.
Namun, pengalaman dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa penetapan taman nasional kerap disertai pembatasan akses dan hak kelola bagi masyarakat setempat.
Inilah yang menjadi sumber kekhawatiran masyarakat adat di wilayah Pegunungan Meratus. Mereka bukan menolak konservasi, tetapi menolak skema pengelolaan yang mengabaikan peran dan hak mereka sebagai penjaga asli ekosistem.
Dalam istilah geografi politik, ini adalah bentuk state territorialization, proses ketika negara mengambil alih kendali penuh atas ruang, sering kali tanpa konsultasi yang memadai dengan pihak yang selama ini mengelolanya secara berkelanjutan.
Konsekuensinya bukan hanya potensi konflik sosial, tetapi juga hilangnya pengetahuan lokal yang terbukti efektif menjaga kelestarian hutan. Jika masyarakat kehilangan hak akses, maka mekanisme sosial-budaya yang menjadi benteng konservasi juga bisa runtuh.
Konservasi Harus Berbasis Tempat
Dalam kajian geografi, ada konsep place-based policy, kebijakan yang dirancang berdasarkan karakter unik suatu tempat, baik dari segi ekologi maupun sosial-budaya. Pegunungan Meratus adalah contoh klasik mengapa pendekatan ini penting.
Alih-alih memaksakan model konservasi seragam, pemerintah seharusnya membangun kerangka kerja yang memadukan sains modern dengan pengetahuan lokal. Misalnya, konsep Indigenous and Community Conserved Areas (ICCAs) atau pengelolaan bersama (co-management).
Skema ini memberi ruang bagi masyarakat adat untuk tetap mengelola wilayahnya sesuai kearifan lokal, sekaligus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kelestarian jangka panjang.
Pendekatan ini telah terbukti di berbagai belahan dunia. Di Filipina, pengakuan Ancestral Domain memungkinkan masyarakat adat mengelola hutan dengan dukungan teknis dari negara.
Di Amerika Latin, model taman nasional bersama masyarakat adat berhasil mengurangi konflik tenurial sekaligus meningkatkan kualitas konservasi.
Modal Sosial dan Pengetahuan Ekologis Masyarakat Adat
Salah satu argumen paling kuat mengapa Pegunungan Meratus tidak boleh hanya dilihat dari kacamata status hukum taman nasional adalah keberadaan modal sosial masyarakat adat. Modal sosial ini mencakup norma, jaringan, dan nilai yang mengatur interaksi antarwarga serta antara warga dengan lingkungannya.
Di Meratus, modal sosial ini terlihat dari berbagai aturan adat yang melindungi hutan larangan, tradisi gotong royong saat membuka lahan, hingga ritual adat yang menandai siklus tanam. Semua ini membentuk ekosistem sosial yang menopang kelestarian ekologis.
Jika kebijakan konservasi menghapus atau membatasi mekanisme ini, maka kita bukan hanya menghilangkan hak masyarakat, tetapi juga melemahkan fondasi konservasi itu sendiri.
Di sinilah letak pentingnya mengakui bahwa konservasi bukan hanya soal melindungi pohon dan satwa, tetapi juga melindungi manusia dan budaya yang telah menjaganya.
Menghindari Konservasi yang Memiskinkan
Salah satu risiko besar dari model taman nasional yang eksklusif adalah fenomena yang disebut conservation-induced displacement, pemindahan atau pembatasan akses masyarakat lokal akibat proyek konservasi.
Dalam banyak kasus, hal ini justru memiskinkan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hutan untuk kebutuhan pangan, obat-obatan, dan bahan bangunan.
Di Afrika dan Asia model konservasi yang tidak inklusif terbukti memicu perlawanan sosial, perambahan ilegal, hingga degradasi lingkungan karena masyarakat kehilangan insentif untuk menjaga hutan. Kita tentu tidak ingin Pegunungan Meratus menjadi contoh berikutnya.
Konservasi yang berhasil adalah konservasi yang menciptakan kesejahteraan bagi penjaga hutannya. Artinya, pelibatan aktif masyarakat adat dalam perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan berkelanjutan bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan.
Merajut Konservasi Bersama
Jika tujuan utama adalah melestarikan Pegunungan Meratus, maka pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih dialogis dan kolaboratif. Saat ini, di beberapa wilayah Pegunungan Meratus, hak masyarakat adat telah mendapatkan pengakuan resmi melalui Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten.
SK ini umumnya menetapkan status kawasan hutan adat atau wilayah kelola adat, memberikan legitimasi hukum atas pengelolaan berbasis kearifan lokal. Pengakuan ini merupakan landasan penting yang harus dijadikan pijakan dalam merancang kebijakan konservasi yang lebih luas.
Jika status taman nasional diberlakukan tanpa mengintegrasikan pengakuan yang sudah ada, maka berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan harmonisasi kebijakan, menyatukan mandat taman nasional dengan SK pengakuan adat, sehingga pengelolaan ruang tetap menghormati hak masyarakat.
Pemerintah provinsi, dan kabupaten perlu membentuk forum koordinasi khusus untuk memastikan bahwa tata kelola hutan adat yang sudah diakui tetap menjadi bagian inti dari strategi konservasi Pegunungan Meratus.
Dengan demikian, penetapan taman nasional tidak berarti mengambil alih pengelolaan, melainkan memperkuat perlindungan yang sudah berjalan, dengan masyarakat adat tetap menjadi garda terdepan penjaga hutan.
Selain itu, perlu dibentuk sebuah badan pengelola yang melibatkan perwakilan masyarakat adat, pemerintah daerah, akademisi, dan LSM lingkungan, untuk merumuskan aturan dan strategi konservasi berbasis data serta kearifan lokal.
Penguatan tata kelola ini dapat dipadukan dengan pemanfaatan teknologi geospasial, seperti peta partisipatif, citra satelit, dan sistem pemantauan berbasis komunitas, sehingga kondisi hutan dapat diawasi secara transparan dan semua pihak memiliki akses pada informasi yang sama.
Upaya konservasi juga harus sejalan dengan pengembangan ekonomi berbasis hutan lestari. Ekowisata berbasis masyarakat, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan pertanian organik yang menjaga fungsi ekologis adalah contoh nyata bagaimana kelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat.
Pegunungan Meratus adalah warisan alam dan budaya yang tak ternilai, dan menjaganya bukan hanya tugas pemerintah atau masyarakat adat semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Cara kita menjaga akan menentukan apakah konservasi menjadi jembatan atau jurang antara negara dan rakyatnya.
Mengubah Meratus menjadi taman nasional tanpa partisipasi masyarakat adat ibarat membangun pagar tinggi di kebun orang lain, secara hukum mungkin sah, tetapi secara moral dan sosial berpotensi menimbulkan luka.
Sebaliknya, konservasi yang mengakui hak, menghargai kearifan lokal, dan memadukan sains modern dengan pengetahuan tradisional akan menjadikan Meratus bukan hanya lestari, tetapi juga menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam.
***
*) Oleh : Selamat Riadi, Dosen Prodi Geografi ULM.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |