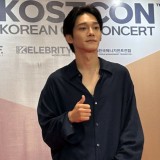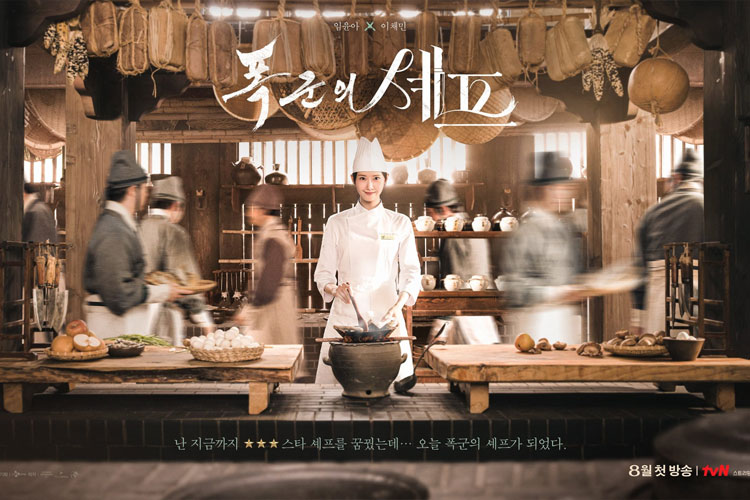TIMES JAKARTA, JAKARTA – Bicara tentang ekonomi masa depan Indonesia bukan sekadar memetakan tren atau memuja angka-angka pertumbuhan. Ini adalah soal arah sejarah, tentang bagaimana kita menyiapkan generasi hari ini agar sanggup menghadapi tantangan esok.
Pertanyaannya, apakah kita sedang membangun ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan, atau justru sedang menyiapkan bentuk baru dari ketergantungan dalam balutan istilah-istilah modern seperti “hilirisasi,” “ekonomi digital,” atau “transisi energi”?
Bonus demografi sering digadang-gadang sebagai modal emas menuju Indonesia Emas 2045. Data Bappenas menunjukkan bahwa puncak bonus demografi Indonesia akan berlangsung antara 2020 hingga 2035, dengan penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai lebih dari 70% dari total populasi.
Namun, sejauh ini, narasi besar itu belum sepenuhnya mewujud dalam strategi konkret. Apa arti bonus jika generasi mudanya tak punya akses pada pendidikan yang relevan? Jika ruang kerja mereka terus digerus oleh kecanggihan mesin dan algoritma, maka yang kita wariskan bisa jadi bukan keuntungan, melainkan ketimpangan sosial.
Indonesia tengah berada di pusaran revolusi digital. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa per 2023, penetrasi internet nasional sudah mencapai 78,19% dari total populasi, tapi ketimpangan digital antarwilayah masih tinggi.
Di balik pertumbuhan startup dan geliat unicorn, ada lebih dari 64 juta UMKM yang sebagian besar belum terintegrasi dalam ekosistem digital. Tanpa dukungan nyata, digitalisasi akan menjauhkan UMKM dari pangsa pasar baru, bukan mendekatkan.
Pertanian, yang menyerap sekitar 29% tenaga kerja (BPS 2023), masih dikerjakan secara konvensional. Padahal, rata-rata usia petani kita kini mencapai 52 tahun. Jika tren ini terus berlanjut tanpa regenerasi dan modernisasi, ketahanan pangan kita akan rapuh.
Teknologi seperti drone pertanian, sensor cuaca, dan sistem irigasi otomatis harus didorong sebagai bagian dari kebijakan publik, bukan sekadar proyek pilot di brosur kementerian.
Sementara itu, hilirisasi menjadi strategi unggulan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir. Ekspor produk nikel olahan meningkat signifikan dari USD 2,1 miliar (2019) menjadi USD 30 miliar pada 2022 (Kementerian ESDM), sebagian besar berkat larangan ekspor bijih mentah.
Tapi kita perlu mengkritisi: siapa yang paling diuntungkan? Apakah Indonesia mendapatkan transfer teknologi dan nilai tambah industri, atau hanya menjadi basis produksi murah bagi industri kendaraan listrik global?
Isu energi pun menjadi pertaruhan besar. Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission pada 2060, namun pada 2023, sekitar 60% listrik nasional masih berasal dari batu bara. Meski potensi energi terbarukan kita sangat besar panas bumi 24 GW, surya 207 GW, angin 60 GW (IESR, 2023) investasi dan realisasi pemanfaatannya masih minim. Transisi energi memerlukan roadmap yang tidak hanya ambisius, tetapi juga adil bagi semua pihak, termasuk pekerja sektor batu bara.
Urbanisasi yang terus meningkat dengan 56% populasi tinggal di kawasan perkotaan per 2023 dan diproyeksikan mencapai 70% pada 2045 (Bappenas) memaksa kita berpikir ulang tentang arah pembangunan kota.
Kota bukan sekadar pusat ekonomi, tapi juga ruang hidup. Konsep smart city, transportasi hijau, dan ekonomi sirkular perlu didorong sebagai strategi inti, bukan sekadar wacana konferensi.
Pendidikan adalah fondasi ekonomi masa depan. Namun, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023 mencatat bahwa sekitar 10 juta angkatan kerja masih bekerja di bawah tingkat pendidikan mereka.
Kita butuh transformasi kurikulum vokasi, kolaborasi antara industri dan pendidikan tinggi, serta penguatan sistem pembelajaran sepanjang hayat agar SDM kita tak sekadar menjadi tenaga kerja murah, tapi kreator inovasi.
Tak kalah penting adalah memastikan bahwa perempuan dan anak muda benar-benar dilibatkan. Menurut McKinsey, peningkatan partisipasi perempuan di sektor formal dapat menambah PDB Indonesia sebesar USD 135 miliar pada 2025.
Namun hingga kini, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih stagnan di angka 54% (BPS 2023). Ekonomi masa depan hanya bisa inklusif jika seluruh potensi diberi ruang yang setara.
Tata kelola fiskal pun harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan. Pada 2023, defisit APBN masih dijaga di bawah 3% terhadap PDB, namun struktur belanjanya masih cenderung konsumtif. Investasi dalam infrastruktur hijau, pendidikan, dan kesehatan harus diperkuat, bukan terus ditekan demi menjaga citra makroekonomi jangka pendek.
Hubungan ekonomi Indonesia dengan dunia pun perlu dibangun secara strategis. Kita kini terikat dalam berbagai kerja sama perdagangan dari ASEAN hingga RCEP. Namun, nilai ekspor kita masih didominasi oleh komoditas mentah dan produk berteknologi rendah.
Artinya, posisi tawar kita masih lemah. Strategi industrialisasi berbasis teknologi tinggi harus didorong, agar kita tidak lagi berada di ujung paling bawah rantai pasok global.
Pandemi menjadi pelajaran mahal tentang arti resilien. Ketika global supply chain terguncang, negara yang mampu bertahan adalah mereka yang memiliki kemandirian pangan, kesehatan, dan industri strategis. Kita tidak bisa lagi bergantung penuh pada impor untuk kebutuhan dasar. Ekonomi masa depan adalah ekonomi yang mampu berdiri di tengah badai.
Kecerdasan buatan dan bioteknologi akan menjadi medan pertempuran masa depan. Namun pada 2022, investasi R&D Indonesia masih di bawah 1% dari PDB, jauh tertinggal dibanding negara tetangga seperti Malaysia (1,44%) atau Korea Selatan (4,8%). Jika kita tidak segera meningkatkan investasi di bidang ini, maka kita hanya akan menjadi penonton dalam revolusi berikutnya.
Namun semua mimpi besar itu akan kandas jika institusi publik kita lemah. Korupsi, kebijakan tambal sulam, dan birokrasi yang kaku masih menjadi penghambat utama transformasi ekonomi.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 berada di skor 34 dari 100 (Transparansi Internasional), stagnan dibanding tahun sebelumnya. Tanpa tata kelola yang bersih dan profesional, semua rencana strategis hanya akan berhenti di slide presentasi.
Masa depan ekonomi Indonesia bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi soal arah keberpihakan. Kita bisa memilih menjadi negara konsumen yang pasif, atau negara pencipta yang mandiri.
Keberanian untuk mentransformasikan kebijakan hari ini akan menentukan posisi kita dalam peta dunia esok hari. Karena ekonomi masa depan bukan ditentukan oleh takdir, melainkan oleh pilihan dan keberanian untuk mengambilnya.
***
*) Oleh : Abdullah Fakih Hilmi AH, S.AP., Akademisi dan Wirausahawan.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
______
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |