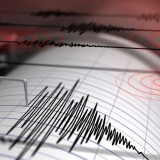TIMES JAKARTA, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 membikin persoalan hukum yang begitu kompleks. Tidak hanya menyangkut rekayasa konstitusional (constitutional engineering) yang akan dibuat, putusan ini juga menghidupkan ulang diskursus lama tentang utak-atik kekuasaan kehakiman.
Pada Sabtu (5/7/2025), DPR membuka kembali peluang untuk merevisi UU MK buntut sejumlah putusan yang menuai polemik dan kontroversi. MK dianggap terlampau jauh melakukan yudisialisasi politik (the judicialization of politics) terhadap sejumlah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Padahal hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga legislatif.
Ada sejumlah isu krusial di balik wacana revisi UU MK, di antaranya: (i) persyaratan batas minimal usia hakim MK; (ii) evaluasi kehakiman; (iii) unsur keanggotaan majelis kehormatan MK, dan; (iv) ketentuan peralihan masa jabatan hakim MK.
Revisi UU MK menjadi ancaman nyata bagi independensi kekuasaan kehakiman. Sejumlah pasal krusial akan menjadi bantalan legitimasi untuk aksi-aksi pelemahan kelembagaan yudisial. Urusan yudisial menjadi mudah untuk dipolitisasi dengan melakukan evaluasi berkala terhadap hakim-hakimnya.
Dalam posisi demikian, wacana revisi UU MK sejatinya merupakan bentuk wacana sistemik yang berusaha melegitimasi pelemahan demokrasi melalui bentuk politisasi yudisial (politicization of the judiciary). Pembajakan semacam ini dilakukan dengan membentuk relasi kuasa dominatif yang membayang-bayangi independensi kinerja hakim dalam memutus perkara.
Pada perkembangan mutakhir, Bisarya dan Rogers (2023) memformulasikan sejumlah modus dan bentuk pelemahan terhadap demokrasi. Salah satu yang banyak dijumpai berupa pelemahan konstitusi, mengubah komposisi hakim, dan memanipulasi lembaga peradilan. Bentuk-bentuk pelemahan tersebut paling memungkinkan dengan melakukan utak-atik terhadap undang-undang yang berlaku.
Tidak terkecuali saat ini di mana MK aktif melakukan aktivisme yudisial dengan aktif terlibat mewarnai kebijakan politik. Pada gilirannya hal itu memposisikan yudisialisasi politik vis-a-vis politisasi yudisial. Membayangi MK dengan ancaman kemerdekaan dan independensi kehakiman. Artinya, intensitas praktik yudisialisasi politik mengakibatkan MK rentan dengan politisasi yudisial.
Makna Putusan Progresif MK
Perseteruan yudisialisasi politik vis-a-vis politisasi yudisial harus segera diakhiri. Sebagian besar legislator yang menganggap praktik yudisialisasi politik melampaui kewenangan MK perlu ditinjau ulang. Pasalnya, hal itu berdampak serius terhadap tatanan demokrasi dan relasi kelembagaan negara.
Sejumlah putusan progresif MK haruslah diletakkan dalam kondisi yang objektif. Pasalnya, MK memiliki batas limitatif untuk mengadili perkara-perkara politik melalui pengujian undang-undang. Batasan itu sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan bukan ketidakadilan yang bersifat intolerable.
Putusan 135/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang tidak tunggal. Sebelumnya terdapat Putusan 85/PUU-XVII/2019 sebagai satu rangkaian satu-kesatuan. MK jelas menyebut desain keserentakan pemilu adalah ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Jika didapati persoalan hukum dalam praktik pemilu serentak, maka perubahan model keserentakan harus melalui lembaga perwakilan.
Tetapi dalam perjalanannya, pembentuk undang-undang tidak responsif menyambut judicial order yang dibuat oleh MK dalam Putusan 85/PUU-XVII/2019. Banyaknya persoalan sistemik pelaksanaan pemilu serentak dengan lima kotak tidak membuat DPR segera merevisi UU 7/2017.
Padahal, pemilu serentak jelas mengakibatkan beban kerja penyelenggara menumpuk dan tidak proporsional dalam jangka lima tahun. Pada gilirannya, banyak dijumpai penyelenggara pemilu (ad hoc) yang gugur dalam menjalankan tugas.
Tidak adanya itikad politik (political will) DPR mengurai persoalan kepemiluan, mendorong MK bergeser pendirian dengan segera menentukan desain konstitusional pemilu serentak. Hematnya, MK justru baik hati dengan mengisi kelalaian DPR memperbaiki sistem pemilu yang bermasalah.
Dengan demikian, di balik putusan yang progresif, MK melakukan praktik yudisial untuk mengisi kevakuman lembaga legislatif dengan menyelesaikan persoalan kebijakan hukum terbuka. Hal itu penting untuk dilakukan dalam rangka mengakhiri segera mungkin kebijakan politik hukum yang implementasinya melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Hingga kapan pelanggaran tersebut diakhiri jika MK tidak melakukan yudisialisasi politik dalam putusannya?
Maka, yudisialisasi politik bukanlah praktik penyimpangan terhadap atribusi kewenangan MK. Tidak seharusnya DPR merespons praktik tersebut dengan mewacanakan politisasi yudisial melalui revisi UU MK.
Kelembagaan MK menjadi benteng terakhir pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional right of citizens). Sesuai amanah Pasal 24 UUD 1945, keberadaan MK harus dimurnikan dari segala bentuk politisasi dan dominasi.
Benah Diri
Alih-alih mewacanakan politisasi yudisial sebagai respon terhadap yudisialisasi politik, DPR sudah seharusnya berbenah diri. Belakangan ini kerja legislasi DPR bersifat akomodatif dan nihil partisipatif.
Sejumlah rencana RUU ditetapkan tidak berdasarkan prioritas kebutuhan hukum masyarakat, tetapi untuk mengakomodasi kebutuhan legislasi awal adanya agenda-agenda politik yang kontroversial. Akibatnya, proses legislasi semakin menjauh dari nurani dan keinginan masyarakat.
Secara bersamaan, MK menjadi tumpuan tunggal masyarakat dalam penegakan demokrasi. Segala persoalan yang ada diadukan secara simultan melalui mekanisme pengujian undang-undang.
Peran MK semakin sentral dalam lanskap politik belakangan. Bersamaan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, MK mewujud institusi tunggal dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga negara.
Maka, langkah revisi UU MK dengan pasal krusial di dalamnya hanya akan membikin krisis konstitusional dan krisis kepercayaan masyarakat. DPR cukup berbenah diri dengan mengaktivasi ekosistem legislasi yang partisipatif dan akomodatif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.
Biarkan yudisialisasi politik menjadi praktik kekuasaan yudisial ketika pembentuk undang-undang justru vakum dan gagal menjawab sejumlah persoalan kebijakan hukum yang dihadapi. Artinya, praktik yudisialisasi politik dapat menjadi alternatif bagi kebijakan politik dan hukum yang berkeadilan.
***
*) Oleh : A. Fahrur Rozi, Akademisi dan Pegiat Konstitusi.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |