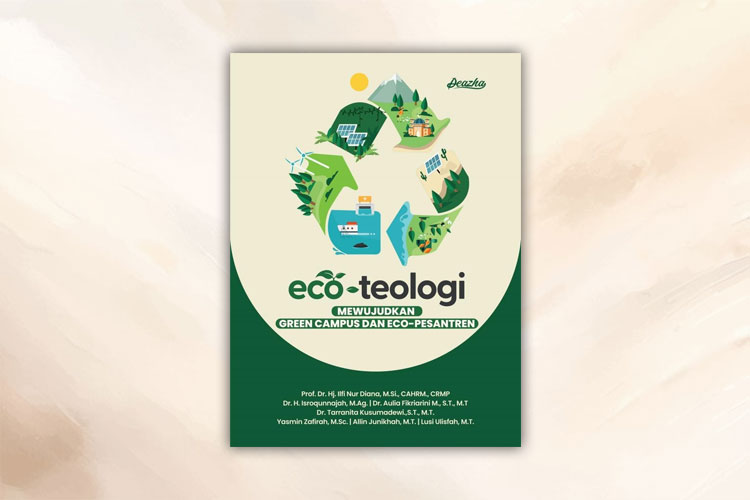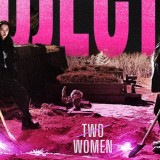TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dunia semakin dilanda krisis ekologi global. Mulai dari pemanasan global, polusi, hingga deforestasi. Nah buku “Mewujudkan Green Campus dan Eco-Pesantren” (2025) hadir sebagai panduan reflektif dan transformatif bagi lembaga pendidikan Islam.
Ditulis oleh tim penulis lintas disiplin yang diketuai oleh Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, buku ini bukan hanya sekadar kumpulan teori. Buku ini menjadi sebuah ajakan tulus untuk menanamkan kesadaran ekologis ke dalam relung spiritualitas kampus dan pesantren.
Buku ini patut diapresiasi karena dengan sangat sistematis mengintegrasikan nilai-nilai teologis Islam dengan praktik-praktik keberlanjutan. Para penulis menyadari bahwa lembaga pendidikan Islam, baik pesantren maupun perguruan tinggi, memiliki potensi besar dalam menumbuhkan budaya ekologis, karena berakar pada sistem nilai yang kokoh dan memiliki pengaruh moral yang kuat terhadap masyarakat.
Seperti tertulis dalam pengantar (hal. iii), “Islam melalui al-Qur’an maupun Hadits mengajarkan bagaimana beretika pada alam dan lingkungan.”
Inilah benang merah buku ini. Membumikan ekologi sebagai laku spiritual.
Ekoteologi: Titik Temu Iman dan Ekosistem
Bab pertama membuka cakrawala kita pada istilah yang mungkin masih asing di sebagian kalangan, yakni eco-teologi. Eco-teologi didefinisikan sebagai kajian tentang hubungan antara agama dan lingkungan, dalam hal ini Islam dan ekologi (hal. 5).
Menariknya, penulis tidak berhenti pada definisi. Mereka juga mengelaborasi lima prinsip utama eco-teologi Islam (hal. 7–15).
Kelima prinsip itu meliputi: alam sebagai tanda kekuasaan Allah (hal. 8), alam sebagai makhluk Allah (hal. 9), alam sebagai kemaslahatan manusia (hal. 10), manusia sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi (hal. 11), dan larangan untuk merusak alam (hal. 14).
Ayat-ayat Al-Qur’an yang disajikan tak sekadar dikutip, namun ditafsirkan dalam konteks kekinian, seperti QS. Al-Baqarah:30 yang menekankan amanah kekhalifahan manusia untuk menjaga bumi. Etika ekologis yang dibangun pun berlapis: dari tanggung jawab individual hingga sistem sosial yang adil bagi seluruh makhluk hidup.
Pendekatan seperti ini menjadikan buku ini unik, karena tidak berhenti pada jargon religius, melainkan meneguhkan kerangka berpikir yang dapat dieksekusi dalam kebijakan pendidikan.
Eco-Pesantren: Merawat Alam dari Tradisi
Bab kedua dan ketiga mengajak pembaca menyelami praktik nyata eco-teologi melalui gerakan eco-pesantren. Istilah ini mengacu pada upaya pesantren membangun budaya dan sistem yang ramah lingkungan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.
Buku ini menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya tempat mengaji kitab. Juga bisa menjadi pusat transformasi ekologis.
Keunggulan bab ini terletak pada uraian strategi dan model gerakan eco-pesantren (hal. 91–97). Penulis menekankan pentingnya peran pemimpin pesantren, khususnya kiai, dalam menanamkan perilaku cinta lingkungan kepada santri (hal. 99–103).
Di sinilah buku ini menjadi sangat aplikatif. Penulis tidak hanya menyarankan idealisme hijau, tapi juga memberi panduan teknis seperti praktik 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant), pemanfaatan bahan lokal, pembangunan ruang terbuka hijau (hal. 110–150), hingga sanitasi ramah lingkungan (hal. 151).
Dengan demikian, buku ini menempatkan santri sebagai aktor ekologis yang berdaya. Pendidikan akhlak di pesantren tidak hanya tentang adab kepada guru atau sesama manusia, tetapi juga pada bumi dan seluruh ciptaan-Nya.
Green Campus: Etos Ilmu yang Ramah Bumi
Peralihan ke ranah kampus dibahas dalam bab keempat dan kelima, yang fokus pada insersi eco-teologi dalam perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Kampus, sebagai lanjutan dari pesantren, memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi ilmuwan dan profesional yang peduli pada krisis ekologi. Penulis menyarankan agar eco-teologi diintegrasikan ke dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat (hal. 177–179).
Kampus Islam tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga laboratorium sosial tempat nilai-nilai keberlanjutan dihidupkan. Buku ini mengusulkan model green campus yang menjadikan spiritualitas Islam sebagai dasar pembangunan ekosistem pembelajaran, kesejahteraan, dan kesehatan (hal. 191–203).
Konsep ini menarik karena menjadikan eco-teologi tidak sekadar sebagai materi studi, tetapi atmosfer hidup kampus itu sendiri.
Kelebihan utama buku ini terletak pada penyatuan antara logika pembangunan berkelanjutan (SDGs, Asta Cita) dengan paradigma keislaman (hal. 179–181). Kampus rahmatan lil ‘alamin itulah visi yang ingin dicapai para penulis. Yakni sebuah lingkungan akademik yang tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga mengasah nurani ekologis.
Kolaborasi Pentahelix: Menghijaukan Pikiran, Menyuburkan Peradaban
Buku ini tidak menutup diri dalam idealisme institusional. Justru, dalam bab-bab akhirnya, penulis menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix—yakni sinergi antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media (hal. 105).
Strategi ini menjadikan eco-teologi bukan hanya proyek kampus atau pesantren, tapi agenda peradaban yang dapat mengakar ke seluruh lapisan masyarakat.
Di tengah fragmentasi pengetahuan modern dan keringnya spiritualitas lingkungan, buku ini menawarkan solusi dengan membumikan nilai-nilai tauhid ke dalam praktik1 sehari-hari. Ia menjadi penghubung antara spiritualitas dan keberlanjutan, antara zikir dan aksi.
Secara keseluruhan, Mewujudkan Green Campus dan Eco-Pesantren adalah karya yang penting, reflektif, dan sangat relevan dengan tantangan zaman. Buku ini bukan hanya mencerahkan pikiran, tetapi juga menyuburkan visi kolektif umat Islam dalam menghadapi tantangan lingkungan global.
Bagi para pengelola pesantren, dosen PTKI, mahasiswa, pegiat lingkungan, hingga pembuat kebijakan, buku ini adalah sumber inspirasi dan pedoman aksi. Ia mengajak kita semua untuk menanam spiritualitas hijau dalam kehidupan, agar kampus dan pesantren tak sekadar menjadi pusat ilmu, tapi juga pusat harapan bagi masa depan bumi. (*)
| Pewarta | : Rochmat Shobirin |
| Editor | : Khoirul Anwar |