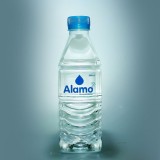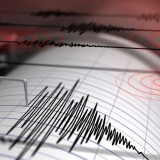TIMES JAKARTA, JAKARTA – Fenomena rangkap jabatan oleh sejumlah Wakil Menteri (Wamen) yang juga merangkap sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengemuka. Dalam sistem presidensial yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, praktik semacam ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah ini bentuk efisiensi pemerintahan, atau justru kemunduran dalam etika konstitusional?
Jika kita menilik lebih dalam, isu rangkap jabatan Wamen tidak semata soal teknis birokrasi, melainkan sudah masuk ke wilayah krusial: krisis etika konstitusional. Krisis ini terjadi ketika nilai-nilai dasar konstitusi seperti integritas, akuntabilitas, dan pemisahan kekuasaan tidak lagi menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
Celah Regulasi dan Kekosongan Norma
Secara normatif, posisi Wakil Menteri diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyebutkan bahwa Wamen adalah pejabat setingkat eselon I dan bukan tergolong pejabat negara.
Formulasi ini menciptakan celah yuridis yang kerap dijadikan pembenaran bahwa Wakil Menteri tidak tunduk pada larangan rangkap jabatan, sebagaimana berlaku bagi menteri dan pejabat tinggi negara lainnya.
Namun argumen ini problematik. Meskipun Wamen secara formal bukan pejabat negara, dalam praktiknya mereka adalah bagian dari lingkar inti kekuasaan eksekutif. Sebagai pembantu Presiden, Wamen memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, logika etika jabatan publik tetap harus melekat dalam fungsi mereka.
Dalam konteks regulasi yang lebih luas, posisi Wakil Menteri juga dapat dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam UU tersebut, Pasal 17 secara eksplisit melarang penyelenggara pelayanan publik untuk merangkap jabatan sebagai pejabat dalam BUMN atau BUMD. Artinya, secara substantif, posisi Wamen tetap berada dalam ruang lingkup pengaturan tersebut.
Lebih lanjut, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memberikan batasan tegas: pejabat negara yang berasal dari kalangan PNS dilarang merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Dimensi Etika Konstitusional
Konstitusi bukan hanya teks hukum, tetapi juga cermin nilai-nilai moral yang melandasi seluruh tata kelola negara. Dalam kerangka ini, etika konstitusional menuntut agar kekuasaan dijalankan secara akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi kepatutan.
Jika ditilik dari sudut etika konstitusional, sebagaimana dijelaskan oleh Ronald Dworkin, konstitusi bukan sekadar himpunan teks legalistik, melainkan cerminan prinsip-prinsip moral yang harus hidup dalam praktik kekuasaan.
Konstitusi mendapatkan maknanya bukan hanya melalui penafsiran yudisial, tetapi melalui perilaku sehari-hari para penyelenggara negara.
Di titik inilah kita menyaksikan krisisnya: ketika jabatan publik diperlakukan sebagai privilese politik yang bisa dibagi-bagi demi kepentingan kekuasaan atau ekonomi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap semangat dan integritas konstitusi.
Krisis ini juga dapat dijelaskan melalui teori Etika Administrasi Negara yang dikembangkan oleh Dwight Waldo. Dalam pandangannya, birokrasi bukanlah entitas yang netral secara teknis, melainkan medan moral yang penuh pertaruhan etis.
Setiap pejabat publik, dalam menjalankan kekuasaan, bukan hanya diminta efisien, tetapi juga bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat yang dilayaninya.
Ketika seorang pejabat merangkap dua jabatan yang memiliki kepentingan berbeda, seperti Wakil Menteri sekaligus komisaris BUMN, maka potensi benturan kepentingan menjadi nyata. Dalam situasi itu, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja birokrasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
Lebih lanjut, prinsip good governance sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997), menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai dua dari delapan pilar utama pemerintahan yang baik.
Rangkap jabatan di posisi strategis kementerian dan perusahaan negara jelas melanggar prinsip tersebut, karena memperbesar ruang abu-abu antara kekuasaan negara dan kepentingan ekonomi. Akibatnya, mekanisme pengawasan menjadi lemah, dan kredibilitas pemerintah dalam mengelola konflik kepentingan dipertanyakan.
Dampak Kelembagaan yang Sistemik
Dampak dari praktik rangkap jabatan Wakil Menteri tidak berhenti pada level individual, tetapi menjalar ke dalam tatanan kelembagaan negara.
Ketika pejabat tinggi publik merangkap jabatan strategis di perusahaan negara, maka yang terganggu bukan hanya performa birokrasi, tetapi arsitektur moral dan tata kelola pemerintahan itu sendiri.
Pertama, praktik ini berkontribusi pada erosinya kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan. Ketika jabatan publik tidak lagi dilihat sebagai amanah, melainkan sebagai ruang akumulasi kekuasaan dan akses terhadap keuntungan, maka kredibilitas negara sebagai entitas yang melayani rakyat mulai dipertanyakan.
Prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi terancam menjadi sekadar slogan tanpa substansi. Akibatnya, jarak antara negara dan warga semakin melebar, dan ikatan kepercayaan yang menjadi fondasi legitimasi demokrasi melemah.
Kedua, praktik rangkap jabatan memperlemah mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal pemerintahan. Seorang Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai komisaris di BUMN menempati posisi ganda yang berisiko besar menciptakan situasi self-regulation, yaitu mengawasi kebijakan dan struktur yang sebagian berada di bawah kewenangannya sendiri.
Ini menciptakan tumpang tindih kepentingan dan menihilkan prinsip checks and balances yang seharusnya menjadi pondasi dalam sistem manajemen sektor publik. Tanpa pemisahan fungsi yang tegas antara pengambil kebijakan dan pelaksana bisnis negara, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin sulit dikendalikan.
Ketiga, dalam jangka panjang, rangkap jabatan dapat menurunkan kualitas pengambilan kebijakan publik. Seorang pejabat yang menjalankan lebih dari satu fungsi penting pada waktu bersamaan berpotensi mengalami beban kerja yang tidak proporsional, gangguan fokus, serta konflik orientasi kebijakan.
Ketika kebijakan publik dikompromikan oleh pertimbangan ekonomi institusional tempat pejabat tersebut terlibat, maka tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat terdistorsi.
Dengan kata lain, rangkap jabatan Wamen bukan hanya problem moral atau etik individu, tetapi simptom dari disfungsi tata kelola pemerintahan. Ia mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara dapat dilonggarkan demi kompromi politik atau kepentingan ekonomi jangka pendek.
Bila dibiarkan, konsekuensinya tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya bagi generasi birokrasi berikutnya.
Reformasi Kebijakan
Mengatasi persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri bukan cukup dengan sekedar memperbaiki celah hukum secara formal. Jika tidak menyentuh akar masalah, yaitu budaya kekuasaan yang permisif terhadap praktik-praktik konflik kepentingan dan oligarki jabatan, kita justru memperpanjang krisis etika konstitusional yang sudah menggerogoti sendi-sendi demokrasi dan tata kelola negara.
Dalam hal ini, perlu adanya langkah-langkah progresif, yaitu: Pertama, pemerintah dan legislatif perlu mempertimbangkan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya dalam memperjelas status hukum Wakil Menteri.
Revisi ini harus menegaskan bahwa Wamen adalah pejabat negara yang tunduk pada prinsip etika publik, dan oleh karenanya dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, terutama dalam lembaga atau korporasi yang memiliki relasi langsung dengan tugas-tugas kementerian. Kejelasan ini penting untuk menutup celah hukum yang selama ini dijadikan pembenaran praktik rangkap jabatan.
Kedua, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki otoritas untuk menerbitkan Perpres atau Keppres yang secara eksplisit melarang Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.
Kebijakan ini tidak hanya akan menunjukkan komitmen Presiden dalam memperkuat integritas kabinet, tetapi juga memberi sinyal positif bahwa pemerintah serius dalam menegakkan prinsip tata kelola yang bersih dan beretika.
Ketiga, DPR dan lembaga pengawasan lainnya seperti KPK dan Ombudsman perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi praktik-praktik kekuasaan yang berpotensi merusak etika kelembagaan.
Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tataran anggaran dan kinerja, tetapi juga pada aspek moralitas jabatan publik. Parlemen yang efektif adalah parlemen yang tidak hanya berbicara soal politik kekuasaan, tetapi juga menjaga kualitas tata kelola kekuasaan.
Rangkap jabatan Wakil Menteri bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, melainkan cerminan dari semakin kaburnya batas antara kekuasaan dan etika. Ketika jabatan publik dijadikan ladang akumulasi kekuasaan dan keuntungan, integritas penyelenggaraan negara akan terus terkikis, dan konstitusi pun kehilangan maknanya sebagai fondasi moral bangsa.
Menjaga etika konstitusional bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Konstitusi atau aparat hukum semata, tetapi kewajiban seluruh penyelenggara negara. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya melindungi institusi, melainkan juga memperkuat kepercayaan rakyat kepada negara dan demokrasi.
Reformasi hukum dan penguatan budaya etika dalam birokrasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan berkeadaban.
***
*) Oleh : Fahmi Aziz, S.H., Pegiat Hukum dan Politik.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |