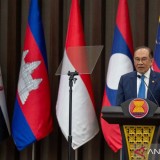TIMES JAKARTA, JAKARTA – Perang dunia modern tidak lagi dimulai dengan deklarasi resmi atau dentuman meriam di medan tempur terbuka. Abad ke-21 menghadirkan wajah konflik yang jauh lebih sunyi namun sistemik. Eskalasi global hari ini bergerak melalui perang proksi, operasi intelijen terselubung, tekanan ekonomi, hingga manipulasi informasi.
Inilah yang dalam kajian hubungan internasional disebut sebagai gray zone warfare ruang konflik yang berada di bawah ambang perang terbuka, tetapi cukup destruktif untuk mengubah arah sejarah dunia.
Rangkaian peristiwa global mutakhir memperkuat kesan tersebut. Dugaan serangan drone terhadap simbol kekuasaan Rusia, eskalasi ketegangan di Amerika Latin, hingga konfrontasi struktural antara Amerika Serikat dan China menunjukkan bahwa dunia tengah memasuki fase pra-operasi konflik global. Bukan sebagai kepastian deterministik menuju Perang Dunia Ketiga, tetapi sebagai pola historis yang berulang: eskalasi kecil yang gagal dikelola, lalu menjelma krisis besar.
Dalam perspektif kekuatan besar, serangan terhadap simbol kepemimpinan negara bukan sekadar insiden keamanan. Ia merupakan eskalasi simbolik yang memaksa negara target merespons, meskipun pelaku dan motifnya masih kabur.
Sejarah konflik internasional menunjukkan bahwa perang besar jarang meletus karena niat awal yang total, melainkan karena ketidakmampuan aktor-aktor global mengelola eskalasi bertahap. Ketika simbol diserang, ruang kompromi menyempit dan logika kekuatan mengambil alih.
Masalahnya, perang modern tidak hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga di ruang persepsi. Dalam perang informasi, kaburnya kebenaran justru menjadi senjata. Klaim, bantahan, dan kontra-narasi berseliweran tanpa verifikasi tuntas.
Ketidakpastian ini menciptakan kondisi yang subur bagi spiral dilema keamanan, di mana langkah defensif satu aktor dibaca sebagai ancaman ofensif oleh aktor lain. Dalam situasi seperti ini, eskalasi dapat terjadi bahkan tanpa niat perang terbuka.
Sejarah memberi pelajaran penting: perang dunia tidak pernah dimulai sebagai perang dunia. Perang Dunia I berawal dari krisis Balkan yang dianggap lokal. Perang Dunia II tumbuh dari rangkaian konflik regional yang gagal diredam.
Bahkan Perang Dingin, meski tidak berubah menjadi perang total, menjadikan Korea dan Vietnam sebagai laboratorium konflik proksi. Pola ini relevan dengan kondisi global hari ini, ketika berbagai kawasan dari Eropa Timur hingga Amerika Latin menjadi arena uji kekuatan global.
Ketegangan Amerika Serikat–China mempertegas bahwa dunia sedang berada dalam fase transisi kekuasaan. Perang teknologi, semikonduktor, Taiwan, dan rantai pasok global bukan isu terpisah, melainkan bagian dari infrastruktur konflik masa depan.
Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, bentuknya kemungkinan besar tidak akan menyerupai perang klasik, melainkan konflik multidimensi yang asimetris, terfragmentasi, dan berlangsung lama.
Di tengah pusaran ini, muncul pula krisis kepercayaan global. Narasi tentang operasi intelijen, false flag, dan elite global sering dianggap teori konspirasi. Namun sejarah membuktikan bahwa manipulasi intelijen bukan hal asing dalam politik internasional. Munculnya teori konspirasi seharusnya dibaca sebagai gejala runtuhnya legitimasi institusi global, bukan semata-mata gangguan diskursus.
Di sinilah dilema Indonesia menjadi relevan. Dalam skenario eskalasi konflik global, Indonesia berada pada posisi sulit sebagai negara menengah dengan kepentingan ekonomi besar dan tradisi politik luar negeri bebas dan aktif. Pilihan Indonesia tidak lagi hitam-putih, melainkan penuh nuansa dan risiko.
Satu kemungkinan adalah kecenderungan soft alignment ke BRICS, terutama di bidang ekonomi, tanpa terikat aliansi militer formal. Ketergantungan ekonomi, dorongan dedolarisasi, dan kerja sama pembangunan alternatif dapat mendorong Indonesia ke arah ini. Namun konsekuensinya adalah meningkatnya tekanan diplomatik dan ekonomi dari Barat.
Pilihan lain adalah mempertahankan strategic ambiguity, yakni tidak berpihak secara tegas pada blok mana pun. Strategi ini memberi fleksibilitas jangka pendek dan selaras dengan warisan bebas–aktif. Namun dalam jangka panjang, posisi ambigu berisiko membuat Indonesia kehilangan pengaruh dan dipersepsikan enggan mengambil sikap dalam isu global krusial.
Indonesia juga berpotensi menjadi arena kompetisi proksi non-militer. Tekanan teknologi, perang narasi di media sosial, serta intervensi ekonomi terselubung dapat menguji kedaulatan digital dan ekonomi nasional tanpa satu pun tembakan dilepaskan. Risiko polarisasi politik domestik pun mengintai.
Skenario yang lebih normatif adalah Indonesia tampil sebagai mediator konflik global. Dengan modal historis Konferensi Asia-Afrika dan kepemimpinan di ASEAN, Indonesia memiliki legitimasi moral untuk memainkan peran ini. Namun peran mediator menuntut konsistensi kebijakan, kohesi domestik, dan keberanian diplomatik yang tidak kecil.
Risiko terbesar adalah involuntary alignment, ketika tekanan struktural global memaksa Indonesia berpihak terlepas dari preferensinya. Sejarah Perang Dingin menunjukkan bahwa banyak negara non-blok akhirnya terseret ke dalam logika blok karena tekanan ekonomi dan keamanan.
Pertanyaan besar hari ini bukan semata apakah dunia menuju Perang Dunia Ketiga, melainkan di posisi mana Indonesia akan berdiri jika eskalasi mencapai puncaknya. Apakah Indonesia tetap menjadi subjek geopolitik yang bebas dan aktif, atau berubah menjadi objek dari konflik global yang tumbuh diam-diam?
***
*) Oleh : Ruben Cornelius Siagian, Peneliti dan Penulis Opini Mengenai Isu Sains-Politik.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |