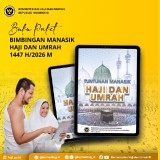TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemilu sering dipuja sebagai pesta rakyat. Ia datang seperti musim panen demokrasi: spanduk meriah, baliho bertebaran, kampanye menggema, dan janji-janji politik menari di telinga publik. Pada hari pencoblosan, rakyat berbondong-bondong ke TPS, mencelupkan jari ke tinta, lalu pulang dengan keyakinan bahwa demokrasi sedang bekerja.
Namun pertanyaan yang lebih jujur harus diajukan: apakah pemilu kita masih menjadi jembatan kedaulatan rakyat, atau justru telah berubah menjadi panggung elite yang hanya meminjam suara rakyat untuk mengukuhkan kekuasaan?
Pemilu sejatinya bukan sekadar pergantian pemimpin lima tahunan. Ia adalah mekanisme agar kekuasaan tidak menumpuk hanya pada segelintir orang. Pemilu menjadi pintu masuk pengambilan keputusan publik agar negara tidak dikuasai oleh mereka yang paling kuat, melainkan dipimpin oleh mereka yang paling layak.
Dalam makna idealnya, pemilu adalah cara rakyat memastikan bahwa kekuasaan tidak membatu menjadi otoritarianisme, tidak mengeras menjadi oligarki, dan tidak menjelma menjadi hak istimewa para elite. Pemilu adalah cara bangsa menjaga agar pemerintahan tetap tunduk pada kehendak warga.
Dua dekade terakhir memperlihatkan kemajuan institusional yang patut dicatat. Pergantian kekuasaan berlangsung damai, penyelenggaraan semakin terlembaga, dan partisipasi pemilih relatif tinggi. Dari sisi prosedural, demokrasi Indonesia tampak semakin mapan. Namun demokrasi tidak cukup dinilai dari ramainya TPS atau tingginya angka partisipasi. Demokrasi bukan sekadar antrean di bilik suara.
Demokrasi adalah soal seberapa jauh suara rakyat benar-benar berpengaruh dalam kehidupan bernegara setelah kotak suara ditutup dan pemenang diumumkan. Di sinilah kegelisahan itu muncul, sebab di balik prosedur yang rapi, terdapat persoalan sistemik yang berulang dan terus menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh.
Persoalan pertama adalah biaya politik yang semakin menggila. Kontestasi elektoral hari ini menuntut ongkos besar: mulai dari biaya pencalonan, kampanye, logistik, konsolidasi jaringan, hingga pengamanan suara. Demokrasi perlahan berubah menjadi barang mahal yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki modal finansial besar.
Fenomena costly democracy ini membuat pemilu tetap berlangsung, tetapi pintu masuknya semakin sempit bagi warga biasa yang punya kapasitas, integritas, dan keberpihakan, namun tidak punya kekuatan dana. Pada titik tertentu, demokrasi seperti pasar besar: siapa yang mampu membayar mahal, dialah yang punya ruang lebih luas untuk tampil.
Tingginya biaya politik sering melahirkan praktik politik uang. Uang dan barang menjadi jalan pintas untuk mengamankan dukungan. Dalam situasi ini, relasi antara pemilih dan kandidat yang seharusnya dibangun atas gagasan dan rekam jejak berubah menjadi relasi transaksional. Pemilih tidak lagi bertanya “apa programmu”, melainkan digiring untuk berpikir “apa yang aku dapat hari ini”.
Ketika pemilu berubah menjadi transaksi, maka akuntabilitas jangka panjang runtuh. Mandat rakyat bukan lagi amanah yang dijaga, melainkan investasi yang harus “dibayar kembali” setelah menang. Di sinilah akar persoalan korupsi politik sering bermula: kekuasaan dipandang sebagai jalan mengembalikan modal, bukan sebagai jalan melayani publik.
Persoalan kedua adalah disinformasi dan polarisasi yang semakin liar, terutama di ruang digital. Era media sosial memang memperluas partisipasi, sebab semua orang bisa bicara, mengkritik, dan menyuarakan aspirasi.
Namun pada saat yang sama, ruang digital juga menjadi ladang racun demokrasi. Hoaks, fitnah, ujaran kebencian, manipulasi emosi, hingga rekayasa digital berbasis bot dan teknologi kecerdasan buatan menjadi senjata baru dalam pertarungan politik.
Algoritma media sosial sering tidak berpihak pada kebenaran, melainkan pada keramaian. Konten yang memicu amarah lebih cepat viral daripada gagasan yang menyejukkan nalar. Akibatnya, pemilu sering dipenuhi pertarungan identitas dan emosi, bukan pertarungan program dan kualitas kepemimpinan. Publik seperti hidup di pasar yang gaduh: semua orang berteriak, tetapi sedikit yang mendengar, apalagi berpikir jernih.
Persoalan ketiga adalah kompleksitas teknis pemilu yang semakin berat. Keserentakan pemilu memang dirancang untuk efisiensi, tetapi dalam praktiknya justru meningkatkan beban administratif penyelenggara dan memperbesar risiko kesalahan prosedural.
Dalam negara sebesar Indonesia, pemilu bukan pekerjaan sederhana. Ia adalah operasi raksasa yang melibatkan jutaan manusia, ribuan pulau, dan logistik yang rumit. Ketika beban terlalu berat, integritas pemilu menjadi rentan terganggu. Demokrasi prosedural bisa tampak berjalan, tetapi rapuh dalam detailnya.
Di titik ini, lahirlah paradoks demokrasi kontemporer: partisipasi pemilih tinggi, tetapi elitisme justru menguat. Rakyat berdaulat ketika mencoblos, namun jarak kembali terbentuk setelah kekuasaan diraih.
Demokrasi menjadi partisipatif dalam prosedur, tetapi elitis dalam struktur. Pemilu seolah menjadi garis akhir demokrasi. Setelah pemilih mencoblos, hasil ditetapkan, kekuasaan berganti, lalu sistem dianggap telah bekerja sebagaimana mestinya. Padahal demokrasi bukan peristiwa sekali jadi.
Demokrasi adalah proses panjang: mengawasi, mengkritik, menagih janji, dan memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan umum. Jika pemilu hanya dimaknai sebagai ritual lima tahunan, maka demokrasi kita akan selalu dangkal—ramai di permukaan, sepi di kedalaman.
Karena itu, mendemokratiskan kembali pemilu tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki teknis penyelenggaraan semata. Pembenahan harus masuk ke jantung tata kelola pemilu, yakni pada struktur yang membentuk relasi antara kekuasaan, modal, dan representasi.
Pemilu demokratis wajib memenuhi dua unsur sekaligus: bebas dan adil. Bebas berarti pemilih tidak berada di bawah tekanan atau manipulasi. Adil berarti arena persaingan tidak condong sejak awal karena keistimewaan struktural yang berlebihan. Jika kesetaraan tidak dijaga, maka pemilu hanya akan menjadi prosedur formal yang menguntungkan kelompok tertentu.
Maka, menjaga kualitas ruang publik menjadi agenda penting agar warga mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi pendanaan politik harus diperkuat agar demokrasi tidak dibajak oleh modal besar.
Pengawasan terhadap politik uang harus lebih tegas, sebab uang yang dibagikan sebelum pemilu sering berubah menjadi utang publik setelah pemilu. Relasi antara kekuatan ekonomi dan jabatan publik juga perlu diatur lebih ketat agar konflik kepentingan tidak merusak kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
Pemilu tidak boleh berhenti sebagai seremoni pencoblosan dan penghitungan suara. Pemilu harus kembali pada hakikatnya: sebagai mekanisme rakyat mengontrol kekuasaan, bukan sekadar alat elite mengamankan posisi.
Demokrasi sejati bukan ketika rakyat diberi hak memilih, melainkan ketika rakyat tetap berdaya setelah memilih. Sebab pemilu yang sehat bukan hanya melahirkan pemenang, tetapi melahirkan sistem yang adil. Dan pemilu yang demokratis bukan hanya menciptakan pergantian kekuasaan, tetapi memastikan kekuasaan tidak menjelma menjadi menara gading yang jauh dari rakyat.
***
*) Oleh : Masykurudin Hafidz, Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |