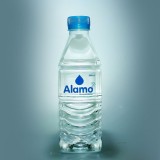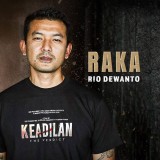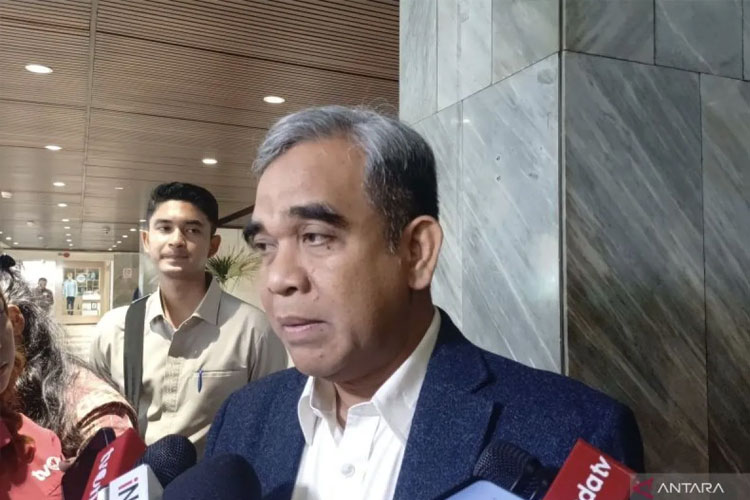TIMES JAKARTA, JAKARTA – Tanggal 18 Agustus 1945 menandai lahirnya konstitusi Republik Indonesia, sebuah dokumen fundamental yang disusun sebagai falsafah bernegara sekaligus pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi ini lahir melalui proses perumusan yang panjang, melibatkan perdebatan mendalam, kajian akademis, dan penyesuaian dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Namun, pada usianya yang ke-80, keberadaan konstitusi seakan terpinggirkan.
Sejumlah regulasi yang semestinya tunduk dan patuh pada amanat konstitusi justru menunjukkan kecenderungan berpaling dan malah mengadopsi prinsip-prinsip komersialisasi dan eksploitasi yang berorientasi pada paham kapitalistik.
Frasa “memajukan kesejahteraan umum” dalam Pembukaan UUD 1945, justru menghadapi kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas kebijakan.
Padahal dalam sistem ketatanegaraan perundang undangan konstitusi memiliki kedudukan tertinggi, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Untuk itu, maka Seharusnya prinsip-prinsip kesejahteraan menjadi pedoman utama penyusunan kebijakan. Namun,pada praktik nya jurang antara konstitusional dan implementasi nyata semakin melebar sehingga menciptakan krisis kepercayaan publik.
Permasalahan Fundamental yang Terabaikan
Dalam konteks global, transisi energi bersih mengalami percepatan, ditandai dengan pertumbuhan kendaraan listrik hingga 60% dalam setahun terakhir. Posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia sebenarnya memberikan peluang strategis.
Pemerintah meluncurkan program hilirisasi industri sebagai dukungan terhadap tren ini. Sayangnya, implementasinya menimbulkan dampak negatif, seperti sengketa lahan, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak masyarakat, terutama di Morowali dan Kepulauan Halmahera.
Temuan WALHI menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan dan peleburan merusak kesehatan warga, ekosistem darat, dan laut, serta merampas ruang hidup masyarakat. Konflik agraria pun meningkat akibat perampasan lahan dan intimidasi.
Alih-alih memperbaiki situasi, pemerintah mengesahkan Revisi UU Minerba pada 19 Februari 2025, yang memusatkan kewenangan izin tambang di pemerintah pusat, sehingga warga terutama di wilayah terpencil semakin sulit menyampaikan aspirasi.
Kesenjangan juga mengakar di sektor ekonomi. Hingga pertengahan 2025, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat 60.000 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dampak lanjutannya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Data CELIOS menunjukkan penurunan Indeks Penjualan Riil dari 222 poin (Desember 2024) menjadi 211,5 poin (Januari 2025).
Di tengah situasi ini, pemerintah justru menaikkan PPh Final menjadi 0,21% dan mewajibkan platform e-commerce memungut pajak otomatis per transaksi melalui PMK No. 50 Tahun 2025.
Kebijakan ini membebani pelaku usaha kecil karena potongan berlaku sebelum perhitungan laba-rugi, yang secara tidak langsung mendorong kenaikan harga jual dan semakin menekan daya beli.
Komersialisasi juga merambah sektor pendidikan. Perguruan tinggi negeri, yang seharusnya menjadi benteng akses pendidikan rakyat, kini berubah menjadi arena eksklusif bagi mereka yang mampu membayar.
Otonomi kampus melalui status PTN-BH sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2012 membuka ruang luas bagi logika komersial. Biaya UKT meningkat, sementara beban mahasiswa bertambah.
Ironisnya, pemerintah justru memangkas anggaran pendidikan tinggi sebesar Rp14,3 triliun melalui Inpres No. 1 Tahun 2025. Pemotongan ini berpotensi memaksa kampus mencari sumber pendanaan tambahan melalui kenaikan biaya pendidikan atau komersialisasi program akademik.
Amanat Konstitusi yang Terlupakan
Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit memandatkan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pasal 28H Ayat (1) menegaskan hak setiap warga untuk hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta akses kesehatan. Pasal 33 Ayat (3) memperkuat bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Namun, praktik kebijakan justru menunjukkan arah sebaliknya. Pemerintah cenderung pro terhadap eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan dampak jangka panjang.
Hal ini memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dan melemahkan fungsi negara sebagai pelindung rakyat. Fenomena ini mencerminkan konsep States of Denial menurut Stanley Cohen, yakni kondisi ketika negara secara sadar mengabaikan penderitaan rakyat.
Legislasi untuk Kesejahteraan
Tidak dapat dipungkiri bahwa Setiap permasalahan dan solusinya dalam kehidupan bermasyarakat pada akhirnya bermuara pada kualitas regulasi yang dibuat pemangku kepentingan. Oleh Karena itu maka setiap proses pembuatan undang-undang harus mengutamakan partisipasi bermakna dari masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif yang mengabaikan aspirasi riil rakyat.
Perumusan regulasi membutuhkan kajian akademis mendalam yang mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat, tidak hanya dari sudut pandang pemerintah. Kajian ini wajib transparan agar publik dapat memahami konsekuensi regulasi terhadap kehidupan mereka.
Transparansi menjadi kunci membangun kepercayaan dan memastikan setiap regulasi mencerminkan kebutuhan rakyat. Sayangnya, unsur-unsur vital ini kerap terabaikan dalam praktik legislasi. Akibatnya, masyarakat merasa haknya tidak dipenuhi dan menyuarakan ketidakpuasan secara tegas.
Kondisi ini menciptakan siklus negatif: kebijakan yang seharusnya menyelesaikan masalah justru memunculkan masalah baru. Maka setiap tahapan perumusan regulasi tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka, tetapi harus dilaksanakan secara substansial dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarkart.
Penerapan konsisten terhadap prinsip ini tentu akan menghasilkan regulasi yang tepat sasaran dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
***
*) Oleh : Muhammad Jundi Fathi Rizky, Mahasiswa Hukum Tata Negara dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Peneliti Distrik Institute.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |