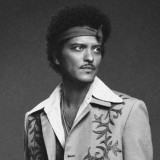TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pagi itu saya membuka komputer dan melihat gambar hasil AI yang memukau. Warna-warna lembut, garis-garis halus, dan nuansa yang sangat mirip dengan gaya Studio Ghibli. Saya terdiam. Bukan karena kagum semata, tapi karena sadar: gaya yang begitu khas itu kini bisa dimunculkan oleh mesin hanya lewat satu baris teks. Tidak ada seniman yang dilibatkan, tidak ada nama yang disebut, apalagi imbalan. Hanya sebuah “prompt”: in Ghibli style.
Di sinilah letak relevansi dari gagasan Style Tag Royalty. Konsep ini merujuk pada mekanisme royalti digital untuk para kreator, saat gaya visual, naratif, atau musikal mereka digunakan sebagai basis dalam sistem AI generatif. Dalam konteks ini, style tag tak sekadar penanda estetika, melainkan bagian dari bahasa yang digunakan AI untuk menerjemahkan gaya ke dalam data instruksi digital.
Polemik di berbagai bidang kreatif menunjukkan bahwa pemahaman ini masih terfragmentasi. Di dunia seni visual, terjadi kontroversi ketika seniman seperti Greg Rutkowski—ilustrator fantasi asal Polandia—mengeluhkan karyanya digunakan secara masif dalam dataset AI tanpa izin. Dalam ranah musik, musisi Grimes menyambut AI dengan menawarkan lisensi terbuka namun tetap menuntut kompensasi; sementara Drake dan The Weeknd sempat 'dihadirkan ulang' lewat suara buatan AI dalam lagu fiksi, memicu debat soal identitas vokal.
Di Indonesia, pembuat batik dan ilustrator lokal seperti Yogyakarta Batik Maker menyuarakan kekhawatiran karena pola khas mereka muncul dalam hasil AI art global.
Contoh-contoh ini memperlihatkan satu hal: bahwa gaya bukan sekadar visual atau bunyi. Ia adalah bahasa. Dan ketika bahasa itu diakses, disalin, atau diubah oleh AI, perlu ada sistem yang memastikan hak penciptanya tetap dilindungi.
Hal serupa kini muncul dalam ranah fotografi realis, terutama dengan pendekatan humanistik dan budaya lokal yang khas Indonesia. Platform generatif seperti ImageFX dan Gemini (Google) menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan citra dengan atmosfer khas Indonesia—dari suasana desa pagi, prosesi adat, hingga ekspresi manusia dalam latar tradisional. Estetika fotografi seperti karya Davy Linggar, Oscar Motuloh, atau Rio Helmi menjadi rujukan tak langsung karena AI menyerap pola visual mereka dalam data pelatihan. Fotografi bukan hanya soal objek yang direkam, tetapi tentang cara melihat dan mengemas cerita melalui bingkai budaya. Jika AI dapat meniru sudut pandang ini tanpa mekanisme pengakuan atau imbalan, maka fotografer sebagai
perekam nilai kemanusiaan ikut terpinggirkan dalam pusaran teknologi.
Dengan makin tingginya minat terhadap citra realisme bernuansa lokal—baik untuk komersial maupun identitas digital—maka sistem style tag royalty juga perlu mengakomodasi fotografi berbasis gaya dan atmosfer. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap sensitivitas visual yang lahir dari konteks sosial-budaya yang tak bisa direplikasi begitu saja oleh mesin.. Ia adalah bahasa. Dan ketika bahasa itu diakses, disalin, atau diubah oleh AI, perlu ada sistem yang memastikan hak penciptanya tetap dilindungi.
Dalam dunia yang semakin terotomatisasi, kita lupa bahwa gaya adalah warisan. Ia lahir dari ribuan jam kerja, dari kekayaan budaya, dari intuisi dan ekspresi manusia. Kini, AI bisa meminjamnya—tanpa permisi. Maka muncul gagasan yang saya sebut Style Tag Royalty. Sebuah bentuk penghargaan yang seharusnya hadir setiap kali gaya seorang kreator dipanggil ulang oleh teknologi. Ini bukan sekadar soal royalti uang, melainkan soal pengakuan.
Bayangkan Anda menulis puisi dengan irama khas Sapardi, atau menggambar dengan gaya ilustratif khas seniman doodle Indonesia seperti Aditya Pratama, yang dikenal lewat karakter 'Papermoon'-nya yang lembut dan ekspresif, atau karya garis enerjik dari Okta Paramita yang menggabungkan pola etnik dengan nuansa kontemporer.
Ketika gaya itu digunakan oleh ribuan orang lain lewat AI, bukankah seharusnya ada sistem yang memberi imbalan, atau sekadar mencatat bahwa Anda penciptanya? Di sinilah keadilan kreatif diuji: bukan tentang siapa yang paling cepat menghasilkan karya, tetapi siapa yang paling konsisten menumbuhkan gaya.
Style Tag Royalty bukanlah gagasan utopis. Secara teknis, kita bisa melacak seberapa sering tag gaya tertentu digunakan dalam platform AI. Kita bisa membangun sistem registrasi gaya, di mana kreator mendaftarkan ciri khas visual, musik, atau naratif mereka. Dan dari sana, pendapatan yang diperoleh platform AI dari pengguna premium, dapat dialokasikan sebagian sebagai royalti. Prinsipnya sederhana: siapa yang memberi nilai, layak mendapat balas.
Negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan mulai membicarakan ini dalam forum-forum etika teknologi. Di Eropa, wacana tentang kepemilikan atas gaya sudah masuk ke ranah hukum intelektual digital. Indonesia, yang sering kali menjadi konsumen budaya digital, sebetulnya memiliki banyak keunikan gaya yang justru menjadi inspirasi global. Kita tidak boleh hanya menjadi penyedia “data pelatihan” bagi sistem AI global, tanpa mendapatkan apapun.
Indonesia sebetulnya punya kekuatan besar di sini. Bayangkan batik, wayang, atau ragam ilustrasi kontemporer yang hari ini makin banyak bermunculan di media sosial. Semua itu adalah aset kreatif. Dan ketika aset ini dipakai oleh teknologi global, kita butuh perlindungan hukum. Kita butuh lembaga seperti Lembaga Manajemen Royalti Digital (LMRD). Kita butuh revisi UU Hak Cipta yang tidak hanya melindungi produk, tapi juga gaya.
Lawrence Lessig pernah berkata, “Creativity thrives when the law protects the creator without hindering innovation.” Kita tidak sedang menolak teknologi. Justru kita ingin teknologi berjalan berdampingan dengan keadilan.
AI bukan musuh. Ia hanya alat. Dan seperti alat lainnya, ia bisa menjadi bermanfaat jika digunakan dengan prinsip etik dan keberpihakan pada manusia.
Kita perlu membangun kesadaran kolektif tentang nilai dari sebuah gaya. Bahasa visual yang menjadi medium utama dalam karya kreatif bukan hanya elemen estetis, tetapi juga memiliki makna dalam konteks semiotika. Roland Barthes, dalam karyanya Mythologies, menyebut bahwa tanda-tanda visual tidak hanya merepresentasikan objek, tetapi menciptakan "mitos"—struktur makna budaya yang tersembunyi di balik representasi sehari-hari.
Ketika gaya kreatif diterjemahkan dalam format digital melalui prompt, sesungguhnya kita sedang mengonstruksi
ulang mitos dalam format baru: mitos digital.
Dalam kerangka ini, prompt AI bekerja sebagai bahasa informatika yang mengambil elemen-elemen dari tanda visual (style, komposisi, warna, atmosfer) dan mengubahnya menjadi citra baru. Ini bukan hanya reproduksi, tetapi reinterpretasi. Seperti Barthes mengingatkan, "Myth is a type of speech," maka prompt juga adalah ucapan yang membawa makna, ideologi, dan referensi budaya. Oleh karena itu, penguasaan terhadap semiotika visual dan pemahaman lintas keilmuan menjadi sangat penting bagi para kreator di era AI. Tanpa itu, mereka bukan hanya kehilangan kendali atas gaya mereka, tapi juga makna dari karya yang mereka ciptakan.
Tanpa pemahaman yang menyeluruh terhadap hubungan antara semiotika visual dan struktur prompt AI, banyak polemik yang muncul bersifat interpretatif dan tidak berdasar. Hal ini terjadi karena minimnya literasi lintas keilmuan di kalangan kreator—antara bahasa desain, informatika, dan hak kekayaan intelektual. Maka, ketika kita mendorong kreator untuk mendaftarkan ciri khas visual, musik, atau naratif mereka, yang kita maksud bukan hanya untuk kepentingan hukum semata, tetapi juga untuk membangun kesadaran atas bahasa mereka sendiri dalam ekosistem digital yang lebih besar dan kompleks.
Dunia akademik bisa memulainya dari kurikulum. Mahasiswa perlu diajak berdiskusi tentang bagaimana AI bisa menjadi mitra kreatif, bukan pengganti. Namun tanggung jawab tidak berhenti pada dunia pendidikan saja. Seluruh elemen yang terlibat dalam praktik industri kreatif—termasuk seniman, desainer, musisi, fotografer, hingga pelaku UMKM berbasis konten digital—perlu memahami konteks baru ini secara integral. Mereka harus didorong untuk tidak hanya melindungi karya mereka, tetapi juga aktif membentuk ekosistem digital yang adil dan etis.
Lebih dari itu, para pemangku kebijakan—baik dari lembaga negara, kementerian, maupun institusi penentu regulasi—perlu duduk bersama dengan pelaku industri dan pengembang teknologi. Dialog lintas sektor ini penting untuk merumuskan kebijakan tata kelola AI yang responsif terhadap perubahan dan berpihak pada keberlanjutan kreativitas manusia.
Kreativitas adalah proses panjang. Gaya tidak muncul dalam semalam. Maka, ketika teknologi menggunakan gaya itu dalam sekejap, kita wajib memastikan bahwa proses penciptaannya tidak dihapus begitu saja. Kita harus menjamin bahwa ada rekognisi. Bahwa sejarah penciptaan tetap tercatat. Bahwa royalti bukan hanya soal uang, tetapi tentang keberlanjutan.
Saya percaya pendidikan vokasi dan seni harus mulai membahas ini. Mahasiswa perlu memahami bagaimana karya mereka bisa hidup di ranah digital—dan bagaimana cara melindunginya. Etika AI bukan sekadar wacana. Ini soal masa depan kerja kreatif.
Style Tag Royalty adalah upaya kecil untuk menjaga keseimbangan. Di tengah euforia AI yang luar biasa, kita tak hanya bicara tentang gambar atau visual. Musik pun kini menjadi arena yang diperebutkan. Kita menyaksikan bagaimana sistem AI seperti Jukebox (OpenAI) dan Suno mampu menghasilkan komposisi musik yang meniru nada, irama, dan bahkan atmosfer khas musisi dari berbagai belahan dunia—termasuk Indonesia.
Coba dengarkan nada pembuka dari musik-musik daerah Nusantara: gamelan Jawa dengan laras pelog dan slendro, tabuhan gendang dari Sulawesi, atau petikan sasando dari NTT. Semuanya memiliki pola yang khas, bukan hanya dari sisi bunyi tetapi dari makna budaya yang terkandung di dalamnya. Ketika AI mulai mengenali dan mereplikasi pola-pola ini dalam bentuk komposisi generatif, maka Indonesia sebenarnya sedang menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga: identitas musikal bangsa.
Di sinilah konsep style tag royalty perlu diperluas tidak hanya untuk visual dan teks, tetapi juga untuk musik. Pola ritmis dan tema musikal tradisional dapat direpresentasikan sebagai style tag, sehingga ketika AI menghasilkan musik dengan nuansa gamelan atau dangdut misalnya, maka negara atau lembaga adat yang menaungi tradisi itu berhak atas royalti.
Hal ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi tentang pengelolaan sumber daya budaya di era digital. WIPO (2023) dalam kerangka kebijakan AI dan kekayaan intelektualnya juga menegaskan pentingnya pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari perlindungan global.
Dengan mencatat pola musikal sebagai aset digital, Indonesia tidak hanya menjaga kedaulatan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Supaya di tengah euforia AI yang luar biasa, kita tak melupakan satu hal: bahwa kreativitas lahir dari manusia. Dan manusia layak dihargai. (*)
Referensi
Barthes, R. (1957). Mythologies. Paris: Éditions du Seuil.
WIPO. (2023). Protecting Traditional Cultural Expressions in the Age of Artificial Intelligence. World
Intellectual Property Organization.
Herlambang, B. (2020). “Nada dan Identitas: Eksplorasi Musik Tradisional dalam Era Digital.”
Jurnal Musikologi Nusantara, 12(1), 33-49.
Lessig, L. (2004). Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down
Culture and Control Creativity. Penguin Press.
Yu, B., & Sakamoto, Y. (2023). “AI-Generated Art and the Ethics of Style Imitation.” Journal of
Digital Ethics and Policy, 8(1), 45-60.
Kusuma, D. A. (2021). “Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Digital di Indonesia.” Jurnal
Hukum dan Teknologi, 6(2), 102-117.
World Intellectual Property Organization (WIPO). (2023). AI and Intellectual Property: A Policy
Framework.
Catatan: Esai ini ditulis sebagai refleksi atas tantangan baru dalam dunia kreatif digital, dan ajakan
untuk membangun sistem yang adil bagi semua kreator.
* oleh: Dr. Redy Eko Prastyo, S.Psi., M.I.Kom
Pengajar Prodi Desain Grafis, Departemen Industri Kreatif dan Digital, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : xxx |
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |