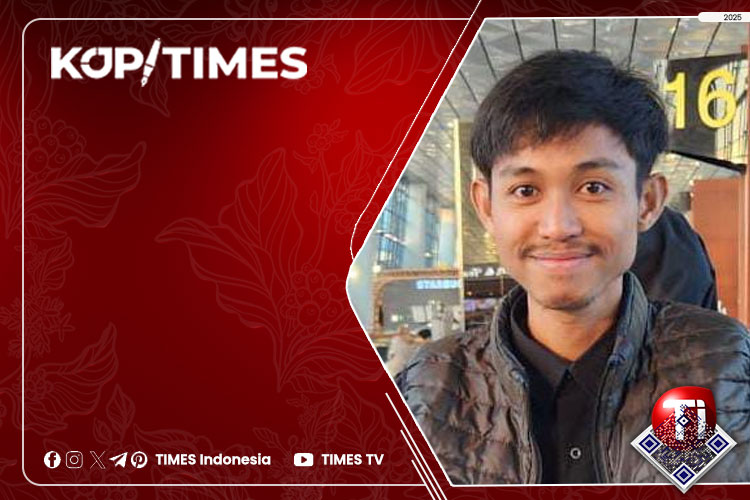TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kasus bunuh diri siswa SD yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) benar-benar membuat hati tertegun begitu dalam. Sehari sebelumnya, ia meminta uang kepada sang ibu. Bukan untuk jajan chiki layaknya anak-anak lainnya, melainkan untuk membeli seutas masa depannya: buku tulis dan pena. Orang tuanya tak memenuhi permintaan kecil itu, bukan tak sudi, melainkan karena keadaan ekonomi yang memaksanya.
Kini, raganya telah terpendam bersama harapannya untuk sekadar memiliki peralatan sekolah yang harganya kurang dari Rp10.000 itu. Ia tinggalkan sepucuk surat terakhir. Ditulis dengan bahasa daerahnya. Bahasa paling jujur yang digunakan oleh anak manusia.
Sepucuk surat tersebut bukan untuk ibunya semata, itu ditulis oleh tangan mungil tersebut agar negara ini mau membacanya secara utuh, sebab selama ini telah terlampau egois, pongah dan bahkan bengis.
Sebelum tragedi ini, Kepala Negara sendiri pernah memamerkan angka kemiskinan pada masa pemerintahannya yang turun ke 8,47 persen per Maret 2025, dan diklaim menjadi rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia.
Tapi realitas kehidupan masyarakat bicara lain, lebih jujur pada sekadar angka-angka statistik itu. Ada seorang anak kecil, yang terlalu dini untuk mengakhiri hidupnya dan mengubur mimpinya, sebab beban kemiskinan ekstrim yang menderanya.
Kemiskinan di Indonesia bukan karena takdir, bukan pula karena sebab kemalasan rakyatnya. Melainkan akibat kebijakan sistemik yang tak berpihak pada jalan keadilan. Maka yang menjadi realitas di Indonesia saat ini, kekayaan yang teramat luar biasa dikuasai oleh hanya segelintir saja.
Negeri kita kaya, namun mayoritas masyarakatnya miskin. Tidak aneh, sebab ini adalah kesengajaan yang memang dipertontonkan oleh kekuasaan.
Kemakmuran, dalam jumlah fantastis dan kolosal di Tanah Air ini hanya dikuasai segelintir elit. Dalam buku #ResetIndonesia (2025) tercatat, pada 2021, harta 40 orang terkaya Indonesia setara dengan total kekayaan 60 juta warga digabung jadi satu. Sekitar 140 juta penduduk hanya menguasai sekitar 5 persen total kekayaan rumah tangga secara nasional.
Ketimpangan juga ditunjukkan lewat penguasaan lahan. Pada 2023, hampir 60 persen lahan dikuasai oleh hanya 1 persen orang/perusahaan. Data dan fakta menyedihkan itu tak pernah menjadi topik pidato di atas podium Kepala Negara.
Realitas itu disembunyikan, digantikan dengan seuntai kalimat fatamorgana, bahwa masyarakat Ibu Pertiwi ini adalah paling bahagia di bumi. Demikian sempurnalah kebohongan itu.
Sembari menormalisasi jurang ketimpangan tersebut, disaat yang bersamaan negara dengan bangganya mempertontonkan program-program populisnya yang menyedot anggaran triliunan dari pajak.
Bagi kekuasaan, persoalan dampak jangka panjang tak terlalu penting, yang utama adalah elektabilitas politik bisa menanjak naik seiring proyek tersebut diberlakukan. Orientasi kebijakan bukan lagi efektifitas, menjawab persoalan sosial-ekonomi rakyat atau tidak, sebab nomor wahid adalah validitas semu.
Lalu, akumulasi dari kebobrokan itu semua, kekuasaan seolah-olah tersentak mendengar kabar kepergian siswa SD tersebut. Kekuasaan tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab atas nyawa yang telah pergi dan tak akan kembali itu.
Kegagalan pemimpinnya pun tak terlalu dipersoalkan. Para pejabat delegasi secara seremonial silih berganti datang ke gubuknya bak pahlawan, menyampaikan belasungkawa, lalu menyerahkan santunan, seolah dosa-dosanya lunas dibayar.
Sepucuk tragedi dari NTT tersebut bukan saja alarm, melainkan adalah pukulan telak pada negeri yang mengklaim paling beradab ini. Negeri ini harusnya malu, mengaku gemah ripah loh jinawi, tetapi buku tulis dan pena seharga nyawa anak bangsa. Masihkah semua dusta dan kemunafikan ini dipertahankan, sampai kapan?
Pertanyaan selanjutnya paling urgen untuk direnungkan dan dijawab adalah, setelah ini apakah negara akan mau benar-benar berubah, menjalankan amanah suci konstitusi? Atau akan kembali menyaksikan anak bangsa satu persatu menggantungkan leher dan harapannya di tiang keputus-asaan, sebab mimpinya untuk hidup dengan layak tak akan juga bisa terwujudkan.
Selamat jalan dik, mohon maafkan kami ini. Tolong jangan adukan negara kami kepada Tuhan di atas sana. (*)
***
*) Oleh : Moh Ramli, Penulis buku Teladan dan Nasihat Islami Paus Fransiskus, jurnalis, dan lulusan Magister Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |