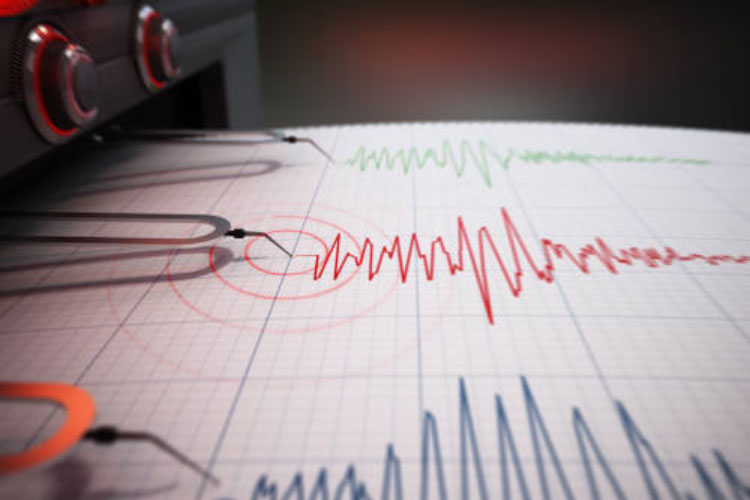TIMES JAKARTA, JAKARTA – Bencana datang tak terduga, namun akarnya sering kali tertanam jauh di dalam keserakahan manusia. Sumatera kembali berduka. Banjir bandang yang meluluhlantakkan Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera Utara bukan sekadar peristiwa alam biasa. Bencana tersebut merupakan manifestasi pahit dari sebuah mazhab ekonomi baru: “Serakahnomics”, yang kini merambah ke ranah eksploitasi alam.
Istilah Serakahnomics yang dikenalkan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus lalu ditujukan untuk memotret praktik ekonomi rakus, seperti korupsi, oplosan BBM, atau skandal ekspor-impor, yang hanya menguntungkan segelintir elite.
Kini, wajah Serakahnomics lebih mengerikan. Eksploitasi tambang dan deforestasi (pembalakan hutan) secara berlebihan di paru-paru kehidupan Indonesia semakin niscaya. Banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah sekitarnya adalah tagihan mahal atas dosa ekologis ini.
Korban Nyata Keserakahan
Data Tim Jurnalisme Kompas yang dirilis 13 Desember 2025 menjadi saksi bisu. Selama periode 1990 hingga 2024, hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah lenyap seluas 1,2 juta hektar, atau rata-rata 36.305 hektar per tahun.
Sumatera Utara mencatat penyusutan tertinggi, mencapai 500.404 hektar. Ke mana perginya hutan itu? Mayoritas dikonversi menjadi lahan sawit (690.777 hektar), kawasan tambang (2.160 hektar), dan hutan tanaman industri (HTI) (69.733 hektar).
Konsekuensinya tampak jelas dalam pola bencana. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan peningkatan tajam kejadian banjir dan tanah longsor. Jika periode 2008-2013 mencatat 780 kejadian, dan 2014-2019 ada 882 kejadian, maka dalam rentang waktu 2020-2025, total kejadian bencana melonjak lima kali lipat menjadi 4.779 kali.
Dampak manusiawi dari tragedi ini sungguh menyesakkan. Hingga 14 Desember 2025, Dashboard Penanganan Darurat BNPB mencatat korban tewas akibat banjir bandang di tiga provinsi Sumatera telah menembus 1.003 jiwa.
Lebih dari 5.400 jiwa luka-luka, dan 218 jiwa masih dinyatakan hilang. Beberapa desa di Aceh bahkan dinyatakan "hilang". Kerusakan fasilitas umum juga masif: 1.200 fasilitas rusak, termasuk 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, dan 145 jembatan.
Hatma Suryatmojo, seorang pakar dari Fakultas Kehutanan UGM, berpendapat bahwa akar utama banjir bandang ini adalah kerusakan ekologis. Arus deras yang membawa kayu, lumpur, dan bongkahan tanah adalah akumulasi dari bertahun-tahun pembukaan lahan di hulu, ekspansi pemukiman, dan alih fungsi hutan. Hilangnya hutan, menurutnya, telah menghilangkan daya serap tanah sehingga debit puncak air tak terkendali.
Serakahnomics sejatinya berhadapan langsung dengan nilai-nilai fundamental dalam teori ekonomi kesejahteraan (welfare economics). Konsep ini, yang mengutamakan akumulasi keuntungan tanpa peduli keadilan sosial, bertentangan dengan prinsip Justice as Fairness dari John Rawls (1971) dalam bukunya A Theory of Justice.
Rawls mengenalkan Difference Principle, yang mengharuskan kemajuan ekonomi diukur dari sejauh mana ia mampu mengangkat kelompok paling tertinggal, bukan sekadar memperkaya segelintir elite.
Ketika eksploitasi alam demi keuntungan segelintir investor (yang notabene masuk dalam praktik Serakahnomics) justru merenggut nyawa, menghilangkan kampung, dan memiskinkan masyarakat di dataran rendah, maka prinsip keadilan Rawls telah hancur lebur.
Lebih lanjut, kerusakan akibat deforestasi ini sangat selaras dengan temuan Prof. Elinor Ostrom dalam karyanya Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (1990), Ostrom, peraih Nobel Ekonomi. Ia mengemukakan bahwa kegagalan dalam mengatur sumber daya milik bersama (commons), seperti hutan, akan menyebabkan tragedi sumber daya (tragedy of the commons).
Individu atau kelompok tertentu yang bertindak demi kepentingan diri sendiri justru merusak sumber daya yang vital bagi seluruh komunitasnya (dalam hal ini bangsa). Serakahnomics adalah contoh nyata dari kegagalan negara dan etika dalam mengelola sumber daya bersama ini.
Ujian Ekoteologi Bangsa
Tragedi ini juga merupakan ujian ekoteologi bagi bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang religius, namun keserakahan yang mewujud dalam deforestasi masif menunjukkan bahwa ajaran agama tentang menjaga alam (hifzh al-bi'ah) hanya tinggal jargon.
Ekoteologi, adalah term yang menghubungkan spiritualitas dengan ekologi, menekankan bahwa alam adalah manifestasi keagungan Tuhan yang wajib dirawat, bukan dieksploitasi.
Sejatinya, menjaga alam adalah bagian integral dari maqashid syariah, khususnya hifzh an-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh al-mal (menjaga harta). Merusak hutan hingga menyebabkan bencana yang merenggut nyawa adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai fasad fi al-ardh (kerusakan di muka bumi).
Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 41, yang pada intinya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kerusakan alam ini secara eksplisit dikaitkan dengan perbuatan manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) yang berkewajiban memakmurkan, bukan merusak.
Ketika Ormas Keagamaan Mendapat Jatah Tambang
Di tengah krisis ekoteologi ini, muncul ironi yang memilukan. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, yang seharusnya menjadi penyeimbang moral dan mengkritisi kebijakan eksploitatif, kini dihadapkan pada "ujian" Serakahnomics.
Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan prioritas bagi Ormas Keagamaan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) menuai kontroversi. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan, namun realitasnya bisa menjebak ormas dalam lingkaran Serakahnomics itu sendiri.
Ketika salah satu ormas (PBNU misalnya), menerima jatah tambang batu bara seluas 26.000 hektare eks PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur, muncullah pertanyaan kritis: Kemanakah peran ormas sebagai penyeimbang moral bangsa?
Ketika Ormas yang mengusung nilai-nilai keislaman moderat dan rahmatan lil alamin terdiam dalam isu eksploitasi alam di Sumatera, meski jatahnya berada di wilayah lain, ini menunjukkan adanya benturan kepentingan yang mengkhawatirkan. Etika keislaman moderat menuntut Ormas untuk menyuarakan keadilan ekologis di mana pun, bukan hanya di wilayah yang tidak terkait dengan bisnisnya.
Pemerintah tidak cukup hanya minta maaf atau menyalurkan donasi. Bencana ini harus menjadi momentum muhasabah kebangsaan. Perlu adanya langkah strategis seperti rehabilitasi hutan jangka panjang dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku deforestasi dan tambang liar, mutlak diperlukan. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.
Ujian Serakahnomics dan Ekoteologi ini adalah pekerjaan rumah bersama. Kita harus memilih: terus menjadi bangsa yang tunduk pada Serakahnomics dan menanggung tagihan bencana yang tak berujung, atau kembali pada fitrah kemanusiaan sebagai penjaga bumi, sebagaimana tuntunan agama dan nilai-nilai keadilan.
***
*) Oleh : Ali Mursyid Azisi, M.Ag., Founder The Indonesian Foresight Research Institute (IFRI), Pengamat Sosial-Politik, Penulis Buku “Melawan Radikalisme Agama, 2024”.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |