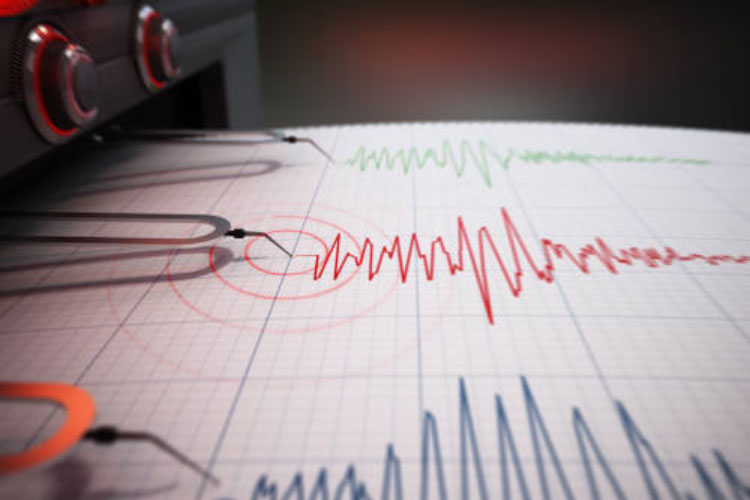TIMES JAKARTA, JAKARTA – Beberapa waktu terakhir, Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi sorotan publik nasional. Bukan semata karena peran historis dan strategisnya dalam menjaga keutuhan bangsa, NU disorot sebab dinamika internal yang kian terbuka dan diperdebatkan di ruang publik. Ketegangan, perbedaan tafsir kewenangan, hingga silang pendapat antar-elit NU memunculkan satu kesan kuat, yakni adanya turbulensi politik organisasi yang tidak bisa lagi dianggap sebagai riak kecil.
Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia bahkan di dunia, NU memikul beban simbolik yang tidak ringan. Setiap keputusan elitnya bukan hanya dibaca sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai pesan moral. Karena itu, konflik internal NU hampir selalu berdampak ganda, baik secara struktural dan juga secara sosiologis. Ia tidak berhenti di meja rapat, tetapi menjalar hingga ke pesantren, majelis taklim, dan percakapan warga nahdliyin di akar rumput.
Dalam kajian sosiologi organisasi, konflik internal bukanlah anomali melainkan bagian dari dinamika institusional. Sosiolog Lewis A. Coser dalam bukunya The Functions of Social Conflict (The Free Press, New York, 1956) menulis “Conflict within a group may serve to reestablish unity and restore the integrative strength of the group, provided that it is regulated by shared norms and institutions.”
Coser menekankan bahwa konflik di dalam suatu kelompok justru dapat berfungsi memperkuat integrasi dan memulihkan kesatuan sosial. Jika konflik tersebut dikelola melalui norma bersama dan mekanisme kelembagaan yang sah.
Sebaliknya, konflik akan berubah menjadi problem serius ketika ia berlangsung lama, bersifat personalistik, dan tidak menemukan kanal penyelesaian yang disepakati. Pada situasi tersebut, kepercayaan publik yang menjadi modal utama organisasi keumatan mulai tergerus.
Disinilah NU sekarang. Turbulensi politik yang kian memanas belakangan ini menempatkan NU pada satu persimpangan penting. Apakah konflik akan dibiarkan berlarut sebagai pertarungan elite, atau diurai melalui jalan konstitusional yang berakar pada nilai-nilai jam’iyah? Apakah wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) akan menjadi jalan keluar institusional atau malah akan menjadi arena kontestasi baru?
Polemik Pasca Pemecatan Gus Yahya Cholil Staquf: Retak di Pusat Otoritas
Polemik internal NU mencuat tajam sejak Rais Aam PBNU mengambil langkah pemecatan terhadap Gus Yahya Cholil Staquf. Keputusan tersebut segera memantik perdebatan luas, baik di kalangan struktural maupun kultural NU.
Persoalannya bukan hanya substansi keputusan, tetapi juga menyangkut prosedur, dasar kewenangan, serta implikasinya terhadap prinsip kepemimpinan jam’iyyah yang selama ini dijaga.
Sebagian kalangan memandang bahwa langkah Rais Aam sebagai bagian dari hak prerogatif kepemimpinan tertinggi dalam struktur syuriyah. Dalam perspektif ini, penegakan disiplin dianggap perlu demi menjaga ketertiban organisasi dan mencegah preseden pembangkangan. Logika yang digunakan cukup sederhana, yakni organisasi besar membutuhkan garis komando yang jelas agar tidak terjebak dalam fragmentasi otoritas.
Namun, pandangan tersebut tidak berdiri tanpa tandingan. Kritik muncul dari mereka yang menilai bahwa keputusan pemecatan itu problematik secara etika organisasi. Pertanyaannya: apakah mekanisme musyawarah telah ditempuh secara memadai? Apakah prinsip kolektif-kolegial yang menjadi ciri khas kepemimpinan NU masih dijadikan rujukan utama? Dan sejauh mana keputusan tersebut mempertimbangkan dampak sosial di tingkat bawah?
Panas. Polemik ini kemudian berkembang melampaui kasus personal. Ia berubah menjadi perdebatan tentang arah kepemimpinan NU secara lebih fundamental.
Sebagian pihak membaca peristiwa ini sebagai indikasi pergeseran dari tradisi deliberatif menuju pola kepemimpinan yang lebih sentralistik. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa apa yang terjadi hanyalah konsekuensi dari transparansi di era digital, ketika konflik internal tak lagi bisa disembunyikan dari publik.
Media sosial mempercepat eskalasi konflik. Pernyataan elit NU dengan cepat dipotong, disebarluaskan, dan ditafsirkan ulang oleh publik. Dalam konteks ini, batas antara kritik internal dan konsumsi publik menjadi kabur. Akibatnya, ruang dialog yang seharusnya tenang dan tertutup justru berubah menjadi arena opini yang hiruk-pikuk.
Dampak polemik ini terasa hingga ke tingkat wilayah dan cabang. Pengurus daerah dihadapkan pada dilema antara menjaga loyalitas struktural atau merespons aspirasi jamaah yang resah.
Di pesantren dan forum-forum informal warga NU, diskusi berkembang liar, mulai dari pembelaan normatif hingga kritik tajam terhadap elit pusat. Semua ini menunjukkan adanya kegelisahan yang belum diartikulasikan secara tuntas melalui mekanisme resmi organisasi.
Oleh sebab itu menurut sempit pemikiran penulis, dari pada bola panas kian bergulir tanpa ampun antara kelompok pro dan kontra harus disatukan pandangan melalui MLB. Karena secara prinsip, MLB adalah mekanisme konstitusional bukan pemberontakan, bukan pula pengkhianatan.
NU sebagai Organisasi Keumatan dan Otoritas Moral Publik
Pada titik inilah, refleksi tentang jati diri NU menjadi krusial. Sejak berdiri pada 1926, NU tidak dirancang semata sebagai organisasi birokratis. Ia lahir sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, organisasi keagamaan yang bertumpu pada nilai-nilai keumatan, kebijaksanaan ulama, dan kepercayaan sosial.
Sejak awal berdirinya, NU dirancang sebagai ruang khidmah. Tempat nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan bertemu. Otoritas NU tidak hanya lahir dari struktur formalnya, tetapi dari kepercayaan umat yang dibangun selama hampir satu abad.
Kepercayaan umat inilah yang membuat NU mampu bertahan melewati berbagai rezim politik, perubahan zaman, dan tantangan ideologis. Karena itu, setiap konflik internal sejatinya harus diukur bukan hanya dari aspek hukum organisasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap otoritas moral tersebut.
Oleh sebab itu, setiap konflik internal NU sejatinya bukan hanya urusan elite, melainkan juga soal tanggung jawab moral kepada warga nahdliyin. Ketika konflik dibiarkan berlarut tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas, yang tergerus bukan hanya soliditas organisasi, tetapi juga wibawa moral NU di mata publik.
Dari sinilah MLB dapat dipahami bukan sebagai ambisi politik, melainkan sebagai ikhtiar etik. MLB menyediakan ruang musyawarah yang sah, terbuka, dan terlembaga. MLB adalah forum yang sejalan dengan tradisi bahtsul masail dan prinsip syura yang selama ini dijunjung NU. Ia memberi kesempatan bagi seluruh elemen untuk bicara, mengevaluasi, dan mengambil keputusan bersama tanpa harus mengandalkan adu pernyataan di ruang publik.
Tentu, Muktamar Luar Biasa bukan tanpa resiko. Ia mengandung potensi polarisasi, biaya sosial, dan kemungkinan konflik terbuka yang lebih tajam. Namun, dalam perspektif etika organisasi, konflik terbuka yang disalurkan melalui forum resmi sering kali lebih sehat dibanding konflik laten yang terus membara tanpa penyelesaian.
Bagi NU, tantangan terbesarnya hari ini bukan sekadar menyelesaikan satu kasus pemecatan atau perbedaan tafsir kewenangan. Tantangan sejatinya adalah menjaga agar dinamika internal tidak menggerus kepercayaan umat. Di tengah turbulensi politik organisasi yang kian mendidih, kedewasaan moral dan kebesaran jiwa para pemimpin menjadi kunci.
Yang diuji bukan siapa benar atau salah, melainkan kedewasaan institusi. NU telah melewati berbagai badai sejarah dari kolonialisme, otoritarianisme, hingga demokratisasi. Turbulensi hari ini seharusnya dibaca sebagai pengingat bahwa kekuatan NU tidak terletak pada figur, melainkan pada mekanisme, etika, dan komitmen kolektif menjaga marwah jam’iyah.
Sejarawan dan pengamat gerakan Islam, Martin van Bruinessen, pernah menekankan bahwa kekuatan NU terletak pada kemampuannya mengelola perbedaan tanpa memutus ikatan sosial. MLB, jika ditempuh dengan niat kebersamaan, dapat menjadi ruang korektif yang bermartabat, ia bukan tanda perpecahan. Tempat seluruh elemen NU berbicara dalam posisi setara, bukan saling menegasikan.
Tentu, tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui MLB. Namun, di tengah turbulensi politik organisasi yang kian mendidih, keberanian membuka ruang musyawarah tertinggi justru dapat dibaca sebagai tanda kedewasaan, bukan kelemahan. Bagi organisasi keumatan seperti NU, menjaga persatuan dan otoritas moral jauh lebih penting daripada mempertahankan gengsi struktural.
Jika MLB akhirnya ditempuh, ia seharusnya menjadi momentum konsolidasi, bukan eskalasi. Momentum untuk menegaskan kembali bahwa NU berdiri bukan untuk kepentingan elitnya, melainkan untuk kemaslahatan umat. Di titik itulah, turbulensi hari ini dapat berubah menjadi pelajaran kolektif bahwa konflik, betapapun kerasnya, masih bisa diarahkan menuju kebijaksanaan.
***
*) Oleh : Nafi’atul Ummah, Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU).
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |