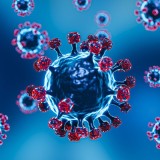TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di tangan waktu, sebagian benda hanya menjadi besi tua. Namun keris memilih jalan berbeda: ia menua tanpa menjadi usang, menua tanpa kehilangan ruh. Setiap tanggal 19 April, bangsa ini kini diajak menoleh pada sebilah logam berlekuk yang tidak sekadar tajam di ujungnya, tetapi juga dalam maknanya.
Hari Keris Nasional, yang ditetapkan Menteri Kebudayaan pada 2025, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pengingat bahwa identitas tidak selalu berwujud gedung tinggi atau teknologi mutakhir kadang ia bersemayam dalam sebilah pusaka yang diwariskan diam-diam dari generasi ke generasi.
Tanggal itu bukan kebetulan. Ia merujuk pada Kongres I Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia di Surakarta tahun 2006, sebuah ikhtiar panjang para penjaga tradisi agar keris tidak hanya hidup di museum, tetapi tetap berdenyut dalam nadi kebudayaan.
Sementara dunia juga mengenal 25 November sebagai Hari Keris Dunia, berkat pengakuan UNESCO, Indonesia memilih menanam tonggak sendiri: bahwa keris bukan sekadar warisan global, tetapi rumah yang tak boleh roboh di tanah kelahirannya.
Dalam sejarah, keris memang senjata. Tapi ia bukan pedang yang haus darah di medan perang terbuka. Ia lebih sering diselipkan, menunggu dengan sabar seperti titik di akhir kalimat tidak selalu terlihat, tetapi menentukan makna. Keris adalah senjata pamungkas, sekaligus pengingat bahwa kekuatan tidak selalu harus berisik.
Namun keris tidak berhenti pada fungsi tikam. Dalam imajinasi kolektif Nusantara, ia menjelma pusaka, tempat spiritualitas menepi sejenak. Banyak orang percaya keris menyimpan energi, memberi ketenangan batin, bahkan menjadi jembatan sunyi antara manusia dan semesta yang tak kasatmata. Ia diperlakukan bukan seperti benda, melainkan seperti tamu tua yang dihormati: dimandikan, diasapi, didoakan.
Di sisi lain, keris adalah bahasa simbol. Ia berbicara tentang status sosial, keberanian, martabat keluarga, hingga legitimasi kekuasaan. Dalam busana adat Jawa dan Bali, keris bukan aksesori, melainkan tanda baca: tanpa kehadirannya, kalimat kebudayaan terasa janggal. Ia melengkapi pengantin, menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua tubuh, tetapi dua silsilah dan dua tanggung jawab sejarah.
Lebih jauh, keris adalah kitab tanpa huruf. Setiap lekuk (dhapur) dan guratan pamor menyimpan filosofi: tentang keseimbangan, kesabaran, kesetiaan, hingga peringatan agar manusia tidak mabuk kuasa. Keris mengajarkan bahwa hidup bukan garis lurus, melainkan berlekuk kadang tajam, kadang landai, tetapi selalu menuju makna.
Kini, keris juga menjelma cenderamata, koleksi, barang estetika. Ia masuk etalase kaca, difoto untuk katalog, diperdagangkan dalam rupiah dan dolar.
Sebagian orang menyebut ini komersialisasi, sebagian lain menyebutnya cara bertahan hidup. Tradisi, seperti manusia, juga perlu makan. Namun di sinilah persoalan bermula.
Kita hidup di zaman ketika budaya bersaing dengan algoritma. Anak muda lebih hafal logo aplikasi daripada pamor keris. Tangan mereka lincah menggeser layar, tetapi gagap saat diminta membaca simbol leluhur. Keris terancam menjadi artefak beku indah, mahal, tetapi bisu.
Digitalisasi memang seperti banjir bandang: membawa kemudahan sekaligus risiko. Jika keris hanya dipamerkan sebagai barang antik tanpa cerita, ia akan redup seperti lampu tua di siang hari. Jika hanya dijadikan suvenir tanpa makna, ia akan kehilangan ruh, tinggal rangka tanpa nyawa.
Tantangan terbesar pelestarian keris hari ini bukan lagi penjajahan fisik, melainkan pengikisan makna. Kita rajin memamerkan bentuknya, tetapi malas merawat filsafatnya. Kita bangga pada pengakuan dunia, tetapi sering lupa menanamkan cinta di rumah sendiri.
Padahal, dunia digital juga bisa menjadi ladang baru. Keris dapat hidup di layar, di film, di gim, di media sosial, di kelas virtual. Ia bisa dikenalkan bukan sebagai benda mistis yang menakutkan, tetapi sebagai narasi budaya yang keren, dalam, dan relevan. Keris bisa menjadi konten, bukan sekadar koleksi.
Pelestarian tidak cukup dengan ritual tahunan dan pidato pejabat. Ia butuh kurikulum, riset, regenerasi empu, ruang kreatif bagi anak muda untuk menafsir ulang tradisi tanpa memutilasinya. Tosan aji tidak boleh dipenjara dalam romantisme masa lalu, tetapi juga tidak boleh dijual murah oleh euforia masa depan.
Keris adalah kompas budaya. Di tengah dunia yang berlari seperti kuda liar, ia mengingatkan bahwa manusia tidak hanya butuh kecepatan, tetapi juga arah. Tidak hanya butuh inovasi, tetapi juga akar.
Hari Keris Nasional seharusnya menjadi lebih dari sekadar tanggal merah di kalender kebudayaan. Ia mesti menjadi jeda kolektif, tempat kita bertanya: masihkah kita mengenali pusaka kita sendiri, atau justru lebih akrab dengan pusaka digital buatan pabrik global?
Sebab jika suatu hari keris hanya tinggal gambar di buku sejarah, maka yang benar-benar hilang bukan sebilah logam, melainkan sepotong jiwa bangsa. Dan bangsa tanpa jiwa, betapapun modern gedungnya, hanyalah kerumunan manusia yang lupa pulang. (*)
***
*) Oleh : Muhammad Hilman Mufidi, Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |